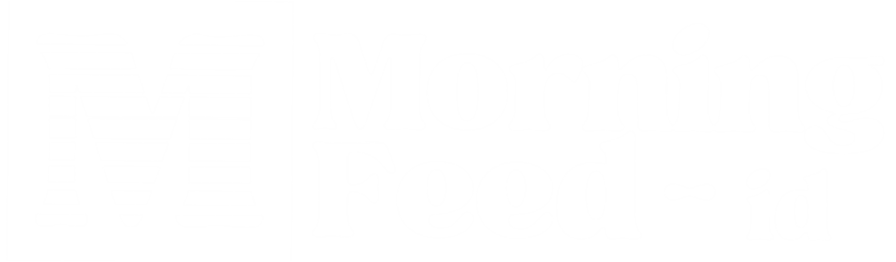Jafar Shodiq (Pusbangkom MKMB)
Bahasa punya cara tersendiri mencatat sejarah. Dari ribuan kosakata yang lahir di tanah air, terdapat dua kata yang menyebrang jauh hingga masuk dalam ke Merriam-Webster Dictionary. Salah satunya amok atau amuck yang berarti mengamuk tanpa kendali. Kata ini lahir dari pengalaman masyarakat Nusantara. Ironisnya, hingga kini masih relevan ketika kita menyaksikan bagaimana massa bergerak.
Fenomena psikologi massa sudah lama diteliti. Gustave Le Bon dalam bukunya The Crowd: A Study of the Popular Mind (1895) menjelaskan bahwa dalam kerumunan, identitas individu larut ke dalam jiwa kolektif. Rasionalitas berkurang, dorongan emosional lebih dominan. Orang yang biasanya tenang dapat berubah impulsif. Satu lemparan batu bisa memicu rentetan lemparan lain. Satu kobaran api bisa mendorong banyak tangan menambah kayu bakar. Inilah kekuatan sekaligus bahaya massa: energi perubahan yang dahsyat, tetapi juga gelombang destruksi yang menakutkan.
Sejarah memberi banyak contoh. Pada masa Romawi, dikenal proscription atau praktik perampasan harta musuh publik dengan legitimasi rakyat. Indonesia punya bab serupa: kerusuhan Mei 1998. Gerakan rakyat kala itu punya arah dan wajah. Ada Amien Rais, Gus Dur, Megawati, dan Sri Bintang Pamungkas. Lawannya jelas: Presiden Soeharto. Kini pola berbeda. Gerakan massa tidak lagi dipimpin figur tunggal, melainkan diarahkan pada institusi: DPR. Bedanya signifikan. Seorang presiden bisa lengser. DPR, dengan segala kelemahannya, tidak dapat dibubarkan begitu saja.
Waktu juga menentukan. Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan pemerintah biasanya hanya punya 2–5 hari untuk meredakan massa. Aksi demonstrasi besar di beberapa negara lain memperlihatkan pola serupa: jika tidak direspons dalam hitungan hari, kemarahan berubah menjadi gelombang yang sulit dikendalikan. Di Indonesia pun begitu.
Dari titik itu, dua jalan terbuka. Pertama, massa mereda dan pemerintah memperbaiki kebijakan. Kedua, massa makin marah dan negara menempuh jalan kekerasan, yang hampir selalu meninggalkan luka panjang: korban jiwa, trauma sosial, bahkan perpecahan.
Namun jangan lupa, massa bukanlah entitas asing. Mereka adalah kita sendiri: tetangga, kerabat, anak muda dengan idealisme, dan orang-orang kecil dengan keresahan dan hadapan hidup. Menjaga agar protes tidak berubah menjadi amuk berarti menjaga martabat kemanusiaan kita sendiri.
Sebagai bangsa, kita telah melalui banyak ujian. Dari 1966, 1998 misalnya hingga gelombang protes sosial pascareformasi. Setiap peristiwa meninggalkan luka, tetapi juga pelajaran. Pertanyaan yang kini mengemuka: bagaimana membangun tradisi protes yang dewasa, yang menekan tanpa menghancurkan, yang bersuara tanpa menyalakan api kebencian.
Di sinilah kita semua diuji. Bukan hanya pemerintah, tetapi juga mahasiswa, masyarakat sipil, tokoh agama, akademisi, hingga media. Kita perlu bersama-sama membangun tradisi protes yang dewasa: menekan tanpa menghancurkan, bersuara tanpa menyalakan api kebencian.
Indonesia sedang melalui ujian besar. Jika kita mampu melewatinya dengan kepala dingin dan hati tenang, sejarah akan mencatat masa ini sebagai tonggak kedewasaan demokrasi kita. Mari jadikan kritik sebagai energi perbaikan, bukan alasan untuk saling melukai. Demokrasi bukan hanya soal kebebasan berbicara, melainkan juga soal tanggung jawab menjaga persatuan dan kemanusiaan.
Jafar Shodiq (Pusbangkom MKMB)