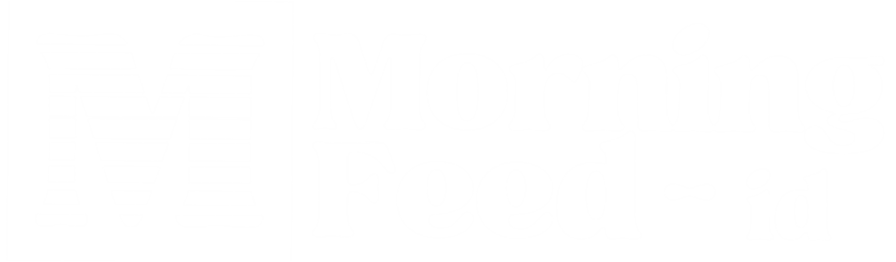Bumi sedang dalam keadaan genting. Data Global Carbon Project 2024 menunjukkan emisi CO2, atau emisi yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak dan gas bumi, serta dari produksi semen dunia, telah mencapai 36,8 miliar ton. Suhu rata-rata global pun naik 1,45 derajat Celsius. Kenaikan suhu yang konon lebih tinggi dibanding era pra-industri.
Sebagai bagian dari dunia, Indonesia pun tidak luput dari kegentingan tersebut. Sepanjang 2024 tercatat lebih dari 2.107 kejadian bencana. Menurut catatan BNPB bencana yang paling banyak terjadi adalah banjir, diikuti oleh tanah longsor dan cuaca ekstrem. Nahasnya, perilaku deforestasi, alih fungsi lahan di pedesaan dan ekspansi industri ekstraktif yang menjadi salah satu penyebab bencana itu tetap dilakukan bahkan semakin signifikan.
Jika kita cermati krisis ekologi yang terjadi itu bukan sekadar urusan yang berkaitan dengan lingkungan. Ia juga adalah cermin dari krisis spiritual, krisis etika sosial, dan krisis cara pandang manusia terhadap semesta.
Beberapa fenomena bencana yang acap kali muncul bukan sekedar pertanda bahwa alam sedang marah. Alam juga mungkin mulai merasa jenuh terhadap cara kita memperlakukannya sebagaimana dikatakan Ebiet G. Ade. Kejenuhan alam yang disebabkan oleh kita yang memperlakukan mereka hanya sebagai objek eksploitasi bukan sebagai bagian dari sesama ciptaan.
Padahal dalam Islam hubungan manusia dengan alam bukanlah hubungan relasi kuasa. Manusia dan alam lebih tepatnya terikat pada relasi amanah. Bumi adalah titipan. Air, tanah, hutan, udara, dan segala yang terkandung di dalamnya bukanlah barang melainkan bagian dari satu kesatuan kosmis yang disebut tauhid.
Ekoteologi
Gagasan ekoteologi yang digaungkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia akhir-akhir ini menawarkan fondasi filosofis yang kuat untuk menata kembali relasi tersebut. Relasi baik antara kita dengan semesta.
Dalam Islam sendiri ekoteologi ini sejalan dengan konsep tauhid, khalifah, dan mizan. Konsep itu merupakan tiga pilar etis yang dapat dikatakan turut membentuk pandangan cendekiawan Islam terhadap lingkungan.
Tauhid menyatukan ciptaan dengan Pencipta. Tidak ada yang profan. Tidak ada yang boleh dieksploitasi secara sewenang-wenang. Khalifah menempatkan manusia dalam posisi sebagai penjaga bukan penguasa. Ia bertugas merawat dan melindungi. Mizan menegaskan bahwa menjaga keseimbangan adalah bagian dari menjalankan perintah Tuhan. Jika keseimbangan itu dirusak maka timbulnya bencana adalah keniscayaan.
Transformasi Moderasi Beragama
Gagasan ekoteologi sendiri digaungkan dengan kesadaran bahwa dalam praktik keberagamaan kesadaran ekologis sering absen. Agama lebih sering direduksi menjadi sebatas aktivitas ritual tanpa refleksi. Tuhan disembah tetapi pada saat bersamaan ciptaan-Nya dirusak. Dalam pandangan spiritual Islam, merusak lingkungan adalah bentuk lain dari fasad fil-ardh atau kerusakan di muka bumi yang dikecam dalam Al-Qur’an.
Gagasan ekoteologi sesungguhnya masih selaras dengan ide moderasi beragama yang telah lebih dulu beredar. Hanya saja kita perlu melihat dan menghadirkan ide moderasi beragama secara lebih luas. Moderasi beragama yang bukan hanya sebagai slogan pemersatu keberagaman tetapi juga sebagai bagian dari etika lingkungan.
Moderasi sejatinya adalah cara hidup yang menolak ekstremisme, baik dalam teologi maupun dalam perlakuan terhadap alam. Jika kita kaitkan lebih jauh maka menjadi moderat berarti menolak penguasaan total atas tafsir dan sumber daya. Menjadi moderat berarti juga menyadari keterbatasan diri, merangkul keberagaman, dan bersikap adil terhadap yang lain, termasuk adil terhadap makhluk hidup dan ekosistem.
Ekoteologi dan Moderasi Beragama
Dalam konsep ekoteologi, sikap moderat adalah elemen penting. Sikap moderat dipergunakan sebagai jalan tengah di antara dua kutub, yakni antara antroposentrisme dan fatalisme ekologis. Kita tidak boleh merasa berkuasa atas bumi tetapi juga tidak boleh pasrah sepenuhnya pada keadaan.
Judith Butler, filsuf kenamaan asal Amerika Serikat, pernah menulis bahwa etika lahir dari pengakuan atas keterikatan kita pada yang lain. Dalam konteks ini “yang lain” bukan hanya manusia tetapi juga makhluk hidup dan lingkungan yang menopang eksistensi kita. Ekoteologi adalah bentuk praksis dari pengakuan itu.
Jika dalam teori performativitas Butler sebuah identitas itu dibentuk melalui relasi yang berulang dengan norma sosial. Maka ekoteologi bisa dibaca sebagai upaya membentuk “identitas keberagamaan” yang lebih etis terhadap alam. Lebih etis karena menjaga lingkungan melalui laku spiritual yang berulang dan sadar akan ketergantungan kita terhadap lingkungan.
Urgensi Ekoteologi
Gagasan ekoteologi di era new normal ini laksana oase di tengah padang pasir. Ekoteologi menawarkan koreksi. Ia mengingatkan bahwa menyelamatkan bumi adalah bagian dari ibadah. Bahkan, ia adalah ibadah itu sendiri. Sebab tak mungkin seorang bertakwa jika ia mengabaikan penderitaan sesama ciptaan Tuhan.
Indonesia, dengan segala keragamannya, punya modal besar untuk memimpin arus baru ini. Tradisi Islam Nusantara yang menekankan harmoni, gotong royong, dan kesederhanaan adalah bentuk awal dari ekoteologi praksis.
Kerja Bersama
Agar semua gagasan itu punya daya ubah dengan arus yang deras dan kuat, kita butuh kerja sistemik. Pendidikan keagamaan harus mengintegrasikan isu-isu ekologi dalam setiap pembelajarannya. Kurikulum moderasi beragama di berbagai Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia harus juga memuat dimensi ekoteologi, selain tentunya tetap mengajarkan pentingnya toleransi antarumat.
Para pemuka agama, pemangku adat aliran kepercayaan, dan pemimpin komunitas harus bicara tentang krisis air, polusi, dan deforestasi sebagai bagian dari dakwah. Setiap ritual keagamaan harus disambung dengan aksi kolektif menanam pohon, membersihkan sungai, dan menolak sikap rakus terhadap eksploitasi alam yang berlebihan.
Kerja bersama itu penting sebab krisis ekologis tidak bisa ditangani hanya dengan melalui sebuah kebijakan. Ia harus disembuhkan dari bawah, dari hal yang paling mendasar, dari akar tingkah laku yakni cara pandang. Dan cara pandang itu dibentuk oleh nilai, oleh ajaran, oleh agama.
Ekoteologi bukan barang baru. Ia hanya tertimbun oleh retorika agama yang sibuk mengurus surga dan neraka tetapi lupa pada keselamatan bumi. Sedangkan menurut Sufi besar Jalaluddin Rumi “Surga bukan tujuan. Surga adalah pantulan dari cara kita merawat bumi ini.”
Sejalan dengan itu, menanam moderasi juga adalah menanam peradaban. Menyiramnya dengan cinta terhadap lingkungan adalah cara terbaik agar ia tumbuh tak sekedar hanya menjadi pohon teduh tapi juga menjadi akar dari kehidupan masa depan yang rahmatan lil ‘alamin.
Bakhrul Amal (Ketua Rumah Moderasi Beragama UIN Raden Mas Said Surakarta)