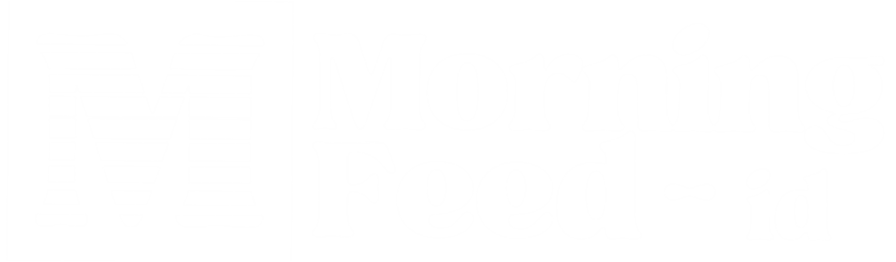Di tengah derasnya arus konten digital, masyarakat Indonesia dihadapkan pada tantangan baru dalam menyikapi kebebasan berekspresi dan konsumsi media. Di satu sisi, kemajuan teknologi memungkinkan siapa pun menjadi produsen konten; di sisi lain, banjir informasi tersebut kerap mengabaikan batas-batas etika, nilai budaya, bahkan martabat kemanusiaan. Dalam konteks inilah, “sensor mandiri” muncul sebagai konsep kunci—sebuah kesadaran kolektif untuk menyaring, memilah, dan menentukan layak tidaknya sebuah konten dinikmati, tanpa harus selalu menunggu regulasi formal dari negara.
Sensor mandiri bukan semata praktik pembatasan, melainkan ekspresi kematangan kultural. Ketika individu atau komunitas memiliki keberanian untuk tidak menyebarluaskan atau menonton konten yang mereka anggap merendahkan nilai-nilai luhur, sesungguhnya mereka sedang membangun benteng budaya. Di sinilah peran literasi media menjadi sentral. Masyarakat yang literat adalah masyarakat yang tahu membedakan antara hiburan dan propaganda, antara kritik sosial dan ujaran kebencian, antara ekspresi artistik dan eksploitasi tubuh.
Namun, kita juga harus jujur bahwa praktik sensor mandiri belum tentu selalu ideal. Dalam beberapa kasus, sensor mandiri berkembang menjadi sensor sosial: tekanan publik, kecaman digital, hingga boikot massal yang kadang mengabaikan proses dialogis. Fenomena ini bisa menjelma menjadi tirani mayoritas—di mana suara-suara minor, ekspresi alternatif, atau kritik yang tidak populer langsung diberangus oleh opini publik. Maka dari itu, sensor mandiri tidak boleh berdiri sendiri; ia harus diiringi dengan etika berpikir, penghargaan atas perbedaan, dan kebijakan negara yang adil.
Peran LSF dan Literasi Budaya
Lembaga Sensor Film (LSF) sebagai institusi negara memiliki peran penting dalam menjaga agar konten film dan audiovisual tidak merusak moral publik. Tetapi di era digital yang memungkinkan distribusi konten secara luas dan cepat melalui platform daring, peran LSF tidak mungkin menjangkau semua. Oleh karena itu, LSF juga menggalakkan program literasi sensor mandiri, menyasar pelajar, guru, mahasiswa, komunitas film, hingga masyarakat umum.
Langkah ini sangat relevan. Alih-alih hanya berfungsi sebagai “penyaring konten”, LSF kini tampil sebagai fasilitator pembelajaran nilai. Sosialisasi nilai-nilai Pancasila, budaya santun, kesetaraan gender, toleransi, dan keadilan sosial dapat menjadi bagian dari kerja kebudayaan yang lebih luas melalui medium film. Dengan kata lain, sensor tidak semata memotong adegan atau melarang tayang, tetapi membangun kesadaran bersama bahwa setiap tontonan membentuk cara pandang dan perilaku sosial.
Sensor Mandiri sebagai Praktik Kultural
Budaya sensor mandiri sebenarnya bukan hal baru dalam masyarakat Indonesia. Dalam dunia pesantren, misalnya, santri telah terbiasa melakukan sensor mandiri dalam membaca teks, memilah referensi, bahkan menahan diri untuk tidak menyebarkan gagasan yang belum matang. Ini adalah bentuk tanggung jawab intelektual dan spiritual yang tumbuh dari kesadaran akan dampak sosial dari sebuah pemikiran atau ekspresi.
Hal serupa juga terjadi di ranah keluarga, sekolah, dan komunitas. Orang tua yang memilihkan tontonan anak, guru yang menyaring bahan ajar sastra, atau komunitas yang mendiskusikan batas-batas kebebasan berekspresi merupakan bagian dari praktik sensor mandiri yang sehat. Tentu saja, ini semua harus didukung oleh akses informasi yang memadai, pendidikan kritis, dan ruang diskusi yang terbuka.
Budaya Pop dan Tantangan Baru
Di era algoritma, budaya pop menjadi kekuatan besar yang memengaruhi selera dan cara berpikir masyarakat, terutama generasi muda. Musik, film, video pendek, dan meme menyebar cepat dengan daya pengaruh yang dahsyat. Namun tidak sedikit dari konten tersebut mengandung kekerasan simbolik, stereotip gender, glorifikasi gaya hidup konsumtif, bahkan nilai-nilai yang bertentangan dengan semangat kebangsaan.
Dalam konteks ini, sensor mandiri menjadi tameng sekaligus kompas. Ketika seseorang memilih untuk tidak menonton film yang merendahkan martabat perempuan, misalnya, atau tidak menyebarkan video yang mengandung ujaran kebencian, maka ia sedang menjalankan tindakan kultural yang besar. Ia sedang menjaga ruang publik dari kerusakan nilai. Maka, penguatan budaya sensor mandiri menjadi bagian dari perjuangan kebudayaan di abad digital.
Perbandingan Sensor Mandiri dengan Sensor Formal di Negara Lain
Untuk memahami posisi budaya sensor mandiri dalam konteks Indonesia, kita perlu melihat bagaimana negara-negara lain menerapkan kebijakan sensor formal dan bagaimana masyarakat meresponsnya. Negara seperti Tiongkok, misalnya, memiliki sistem sensor negara yang sangat ketat. Film-film asing disaring secara sistematis sebelum masuk ke bioskop, sementara film domestik harus melewati beberapa tahap persetujuan yang tidak hanya mempertimbangkan konten seksual atau kekerasan, tetapi juga muatan ideologis dan politis. Di sisi lain, sistem sensor ini memaksa para pembuat film untuk mengembangkan strategi kreatif, seperti penggunaan metafora dan simbolisme, agar tetap dapat menyampaikan kritik sosial tanpa melanggar batas yang ditetapkan negara.
Sebaliknya, Amerika Serikat menganut pendekatan berbeda: sensor formal tidak diberlakukan oleh negara, tetapi oleh lembaga independen seperti MPAA (Motion Picture Association of America) yang memberikan rating berdasarkan usia. Sistem ini memberi kebebasan lebih luas kepada pembuat film, tetapi tanggung jawab pengawasan kemudian bergeser kepada orang tua dan masyarakat. Dalam konteks ini, budaya sensor mandiri menjadi lebih dominan, karena masyarakat sendiri yang menentukan sejauh mana konten dianggap pantas ditonton atau dikonsumsi.
Indonesia berada di antara dua kutub itu. Lembaga Sensor Film (LSF) memang menjalankan peran formalnya dalam menyaring film sebelum tayang, tetapi dalam praktiknya, budaya sensor mandiri juga berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai moral, agama, dan budaya. Hal ini terlihat dari fenomena penolakan masyarakat terhadap film tertentu, bahkan sebelum dinilai secara resmi oleh LSF. Maka dari itu, tantangannya bukan sekadar menyeimbangkan antara sensor negara dan sensor mandiri, tetapi juga memastikan bahwa proses penyaringan ini tidak menutup ruang diskusi, kritik sosial, dan kebebasan berekspresi yang sehat dalam masyarakat demokratis.
Penutup: Menuju Masyarakat Literat, Santun, dan Merdeka
Sensor mandiri bukan instrumen pembungkaman, melainkan sarana pembebasan—yakni membebaskan diri dari keterjebakan tontonan yang merusak, tanpa harus menjadi represif. Dalam masyarakat demokratis yang berakar pada budaya dan nilai luhur, sensor mandiri bukanlah musuh kebebasan, tetapi pendampingnya yang bijak. Karena itu, kita perlu terus membangun ruang-ruang dialog antaraktor kebudayaan: pembuat film, kritikus, penonton, lembaga sensor, dan masyarakat sipil. Literasi media, etika digital, dan pendidikan karakter harus menjadi fondasi bersama.
Pada akhirnya, tantangan sensor mandiri di era digital bukan hanya persoalan konten, tetapi juga soal siapa kita dan apa yang kita perjuangkan sebagai bangsa. Sebuah bangsa besar adalah bangsa yang tahu memilah mana yang perlu ditonton, dan mana yang harus ditinggalkan—bukan karena dilarang, tapi karena sadar bahwa tontonan membentuk cara kita berpikir, merasa, dan bertindak.***
Abdul Wachid B.S. Penulis adalah penyair, Guru Besar Pendidikan Bahasa & Sastra Indonesia dan Ketua Lembaga Kajian Nusantara Raya (LK Nura) Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto.
Esai ini disampaikan pada Sosialisasi Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (“Pengaruh Budaya Sensor Mandiri terhadap Masyarakat”) di Hotel Java Heritage, Purwokerto, Rabu, 18 Juni 2025, 09.00-selesai, diselenggarakan oleh Lembaga Sensor Film (LSF) RI.