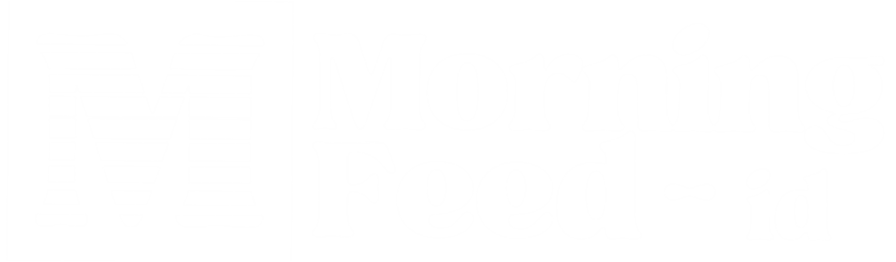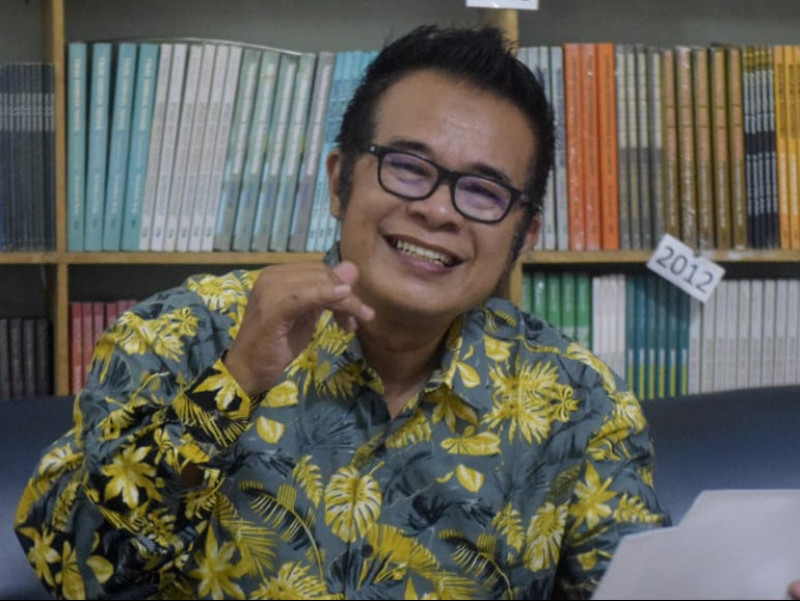Dalam beberapa tahun terakhir, sebuah pergeseran menarik terlihat di kalangan santri muda dan komunitas pesantren. Mereka mulai membuka diri untuk membaca karya sastra modern—bahkan yang tidak bertema religius secara eksplisit—sebagai bagian dari praktik kontemplatif dan reflektif. Forum-forum baca bertajuk “Ngaji Sastra” kini hadir di pesantren, madrasah, hingga komunitas literasi kampus. Karya-karya seperti puisi Chairil Anwar, Sapardi Djoko Damono, dan Rendra menjadi bahan tadabbur kultural. Lalu, apakah ini sekadar tren literasi, atau justru menandai arah baru spiritualitas santri?
Sastra dalam Tradisi Pesantren
Sejak dulu, pesantren sebenarnya memiliki relasi erat dengan sastra. Teks-teks klasik yang dibaca para santri tidak hanya berisi hukum atau akidah, tetapi juga nuansa estetik dan sastra. Kita mengenal Burdah karya Imam al-Bushiri, al-Hikam karya Ibn ‘Athaillah as-Sakandari, atau syair-syair sufistik Hamzah Fansuri yang penuh metafora ilahiah.
Tradisi syi’ir juga mengakar kuat, seperti pada karya-karya Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Serat Wedhatama yang dinisbahkan kepada KGPAA Mangkunegara IV. Semua ini menunjukkan bahwa pesantren sejak awal telah menjadikan sastra sebagai medium spiritual—bukan sekadar pelengkap, tetapi bagian dari jalan ma’rifatullah.
Dalam konteks kekinian, “Ngaji Sastra” menjadi kelanjutan dari tradisi ini. Namun kali ini, teks yang dibaca bukan lagi hanya syair Arab klasik atau Jawa kuno, melainkan puisi modern berbahasa Indonesia.
Ketertarikan Santri pada Sastra Modern
Santri zaman sekarang tak segan membaca puisi-puisi seperti “Aku” karya Chairil Anwar atau “Aku Ingin” karya Sapardi Djoko Damono. Misalnya:
Aku ingin mencintaimu dengan sederhana,
dengan kata yang tak sempat diucapkan
kayu kepada api yang menjadikannya abu
…..
(Damono, Hujan Bulan Juni, 1994)
Atau sajak “Doa” Chairil Anwar yang mengetuk batin:
Tuhanku
Dalam termangu
Aku masih menyebut nama Mu
…..
(Anwar, Deru Campur Debu, Cet.I, 1949)
Bagi sebagian kalangan luar pesantren, ini mungkin dianggap sekuler. Namun bagi para santri, puisi tersebut bisa dibaca sebagai bentuk “wirid” baru: penuh pengakuan, kepasrahan, dan pencarian. Seperti baris Sapardi di atas, “kayu kepada api” bisa dimaknai sebagai metafora fana’: totalitas cinta yang meluruhkan ego. Sedangkan Chairil menyuarakan pengalaman spiritual yang getir namun jujur, seperti zikir seorang hamba yang remuk di hadapan Tuhannya.
Ngaji Sastra sebagai Ruang Tadabbur
Forum-forum seperti “Tadarus Sastra NU”, “Jejak Imaji” di Yogyakarta, atau ruang-ruang di “Pondok Pena” Pesantren An-Najah di Purwokerto, tidak sekadar membaca puisi, tapi juga membedahnya dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani.
Bayani: memahami makna harfiah, struktur bahasa, dan imaji dalam teks.
Burhani: menghubungkan puisi dengan nalar, akal sehat, dan pergulatan rasional—terutama tema eksistensial, cinta, kematian.
Irfani: menyelami makna batin, simbol spiritual, dan kedalaman ruhani yang mengalir dari kata-kata.
Dengan tiga pendekatan ini, membaca puisi menjadi tadabbur, bukan sekadar hiburan. Bahkan “sajak sekuler” pun bisa menjadi wahana untuk mengenali Tuhan—bukan dengan dogma, melainkan dengan kesadaran rohani.
Sastra: Spiritualisasi, Bukan Sekularisasi
Sebagian orang mengkhawatirkan bahwa membuka ruang sastra modern di pesantren bisa menyeret santri ke arah sekularisme. Namun faktanya, fenomena ini lebih menyerupai spiritualisasi bahasa daripada sekularisasi iman.
Gus Dur dalam Islamku, Islam Anda, Islam Kita: Agama, Masyarakat, Negara, Demokrasi (2006) menulis bahwa kebudayaan adalah wadah berkembangnya nilai-nilai keislaman secara manusiawi.
Sastra—dengan bahasa simbolik dan ruang kontemplatifnya—adalah bagian dari kebudayaan tersebut. Maka membaca Chairil atau Sapardi tidak menurunkan kadar keimanan, justru memperkaya jalan spiritual yang lebih manusiawi dan mendalam.
Santri dan Kontemplasi di Tengah Era Distraksi
Di tengah dunia digital yang serba cepat, di mana dakwah pun sering disampaikan dalam potongan video kilat, puisi memberi ruang jeda. Ia menciptakan “kesunyian” dalam batin yang rindu akan keheningan.
Dalam sajak “Doa”, Chairil menulis: “…/Tuhanku// Aku hilang bentuk/ Remuk//…// Tuhanku/ Di pintu Mu aku mengetuk/ Aku tidak bisa berpaling”.
Bait ini seperti doa seorang salik dalam perjalanan sufistik. Chairil, meski dikenal sebagai penyair “pemberontak”, dalam puisi ini justru memperlihatkan jiwa yang takluk dan lebur dalam perjumpaan spiritual.
Sapardi, lewat puisinya yang tenang, mengajarkan tawadu’ dan zuhud. Ia tidak bicara tentang Tuhan secara langsung, tapi membisikkan nilai-nilai ilahiah secara halus. Dalam hal ini, sastra modern menjadi madrasah batiniah yang melengkapi “kitab kuning” di ruang-ruang pesantren.
Santri Membaca Dunia: Melanjutkan Tradisi NU
Fenomena “Ngaji Sastra” menunjukkan bahwa santri tidak menutup diri dari dunia, tapi juga tidak terlarut dalam arus sekularisasi. Mereka memilih jalan tengah: membaca dunia dengan mata iman. Gus Mus mengatakan: “Menjadi santri bukan berarti menutup telinga dari dunia, tetapi menyiapkan hati untuk menampung makna dari dunia.”
Dengan membaca Rendra, Chairil, atau Sapardi, para santri tidak meninggalkan pesantren, tapi justru memperluas dimensi keilmuan dan kepekaan kulturalnya. Inilah bentuk baru dari misi dakwah kultural yang inklusif.
Sebagaimana diungkapkan Sapardi: puisi adalah upaya terus-menerus manusia menyebut Nama-Nya, meski sadar tak akan pernah benar-benar mampu (Damono, Ada Berita Apa Hari Ini, Den Sastro? 2008).
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa puisi bukan sekadar bentuk keindahan, tapi juga laku spiritual yang terus mengarah kepada yang Maha Gaib.
Menjalin Rasional dan Spiritual melalui Sastra
Fenomena “Ngaji Sastra” membuktikan bahwa santri hari ini tidak hanya menjadi penerima teks-teks keagamaan secara pasif, melainkan tampil sebagai pembaca yang kritis, reflektif, dan spiritual. Mereka membuka diri terhadap puisi-puisi modern seperti karya Chairil Anwar, Sapardi Djoko Damono, hingga Rendra—bukan untuk menggantikan “kitab kuning”, tetapi sebagai sarana memperkaya batin dan memperdalam iman.
Sebagaimana dijelaskan Amin Abdullah dalam Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif (2006), pendekatan irfani menempatkan rasa dan pengalaman spiritual sebagai bagian sah dari epistemologi Islam. Dalam semangat ini, puisi modern menjadi ruang tafakur yang tak kalah sakral: mengajak santri mengenal dirinya, Tuhannya, dan kemanusiaannya.
Maka, membaca puisi bukan semata soal keindahan bahasa, melainkan upaya menjalin nalar dan nurani—antara logos dan spiritualitas. Di tengah era distraksi dan fragmentasi, ‘Ngaji Sastra’ menjadi jalan sunyi yang merawat keutuhan diri, menghidupkan batin, dan memadukan iman, akal, serta rasa dalam satu gerakan kontemplatif.
Dengan demikian, ‘Ngaji Sastra’ bukan sekadar ekspresi budaya sesaat, tetapi bagian dari ikhtiar santri hari ini untuk menafsirkan hidup secara utuh—melalui kata-kata yang jujur, jernih, dan menyentuh langit makna.***
Abdul Wachid B.S. (Penulis adalah penyair, Guru Besar Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Ketua Lembaga Kajian Nusantara Raya (LK Nura) di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.)