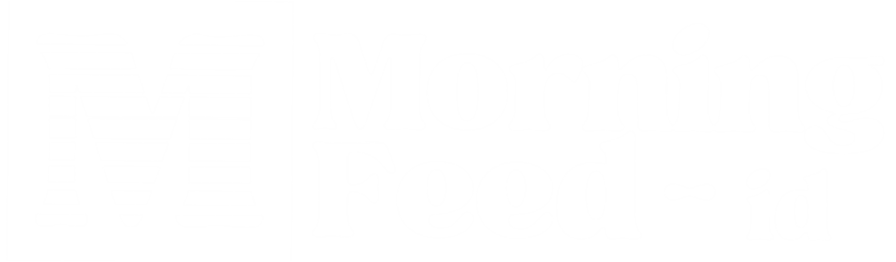Fullday School dalam Lintasan Sejarah
Fullday school bukan sekadar wacana pendidikan yang muncul tiba-tiba, melainkan cerminan dinamika zaman yang terus bergulir. Ada yang memandang fullday school sebagai terobosan pendidikan, tapi ada pula yang khawatirkan berkurangnya waktu anak untuk keluarga dan kegiatan keagamaan. Di tengah polarisasi pandangan ini, ada baiknya kita menyelami akar sejarahnya: bagaimana konsep ini berevolusi dari kebijakan teknis menjadi fenomena sosial yang sarat makna, dan apakah kebijakan ini akan menjadi solusi atau justru masalah baru?
Gagasan fullday school secara formal mengemuka ketika Prof. Muhadjir Effendy memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui Permendikbud No. 23 Tahun 2017, ia memperkenalkan pola lima hari sekolah dengan 40 jam kerja guru per minggu—sebuah kebijakan yang awalnya dirancang untuk optimalisasi waktu tenaga pendidik (Kumparannews, 17 Agustus 2017). Namun, dalam praktiknya, masyarakat membaca ini sebagai “instruksi seragam” yang mengabaikan keragaman konteks geografis dan budaya. Di sinilah letak ironinya: sebuah terobosan administratif justru berubah menjadi ujian bagi fleksibilitas sistem pendidikan kita.
Respons publik pun beragam. Di Kabupaten Pekalongan, penolakan terhadap lima hari sekolah disampaikan secara terbuka oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Fraksi PKB DPRD. Ketua Fraksi PKB, Jahirin, MH, menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan karakteristik pendidikan di wilayah yang kuat akar tradisi keagamaannya. Mereka khawatir pemangkasan hari sekolah akan melemahkan fungsi lembaga-lembaga pendidikan nonformal seperti madrasah diniyah dan pesantren (Suaramerdeka.com, 18 Juli 2025).
Kini, arah kebijakan mulai bergeser. Di era Prof. Abdul Mu’ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, pemerintah menerbitkan Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025. Aturan ini memberi keleluasaan: lima hari boleh, enam hari pun sah—asal total jam belajar terpenuhi. Kebijakan ini lebih lentur, memberi ruang bagi daerah dan satuan pendidikan untuk menentukan model terbaik sesuai konteksnya.
Menariknya, di tengah pro-kontra yang terjadi, banyak madrasah justru membuktikan bahwa fullday school bisa dijalankan secara lentur dan bermakna. MI Jabalul Khoir di Purwodadi, misalnya, tetap memakai pola enam hari, dengan durasi belajar yang cukup panjang setiap harinya. Begitu juga MI NU Mathalibul Huda Mlonggo Jepara, yang mengelola model fullday berbasis pesantren—menggabungkan pembelajaran umum dan keagamaan secara harmonis. Model seperti ini memperlihatkan bahwa fullday bukan soal format baku, tapi tentang sejauh mana sekolah bisa menjawab kebutuhan murid dan komunitasnya.
Regulasi Memberi Ruang Fleksibilitas
Banyak orang mengira bahwa fullday school adalah kebijakan yang seragam dan mengikat. Padahal, sejak awal, aturan yang berlaku justru membuka ruang adaptasi yang fleksibel. Permendikbud No. 23 Tahun 2017 memang menetapkan lima hari sekolah sebagai standar nasional, namun Pasal 10 Ayat (2) secara eksplisit dan tegas memperbolehkan pelaksanaan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing sekolah.
Kini, melalui Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025, pendekatan itu diperkuat dan diperdalam. Fokus kebijakan tidak lagi pada jumlah hari belajar, melainkan pada totalitas waktu pembelajaran yang menyesuaikan jenjang pendidikan dan kebutuhan lokal. Misalnya, SD kelas I ditetapkan menempuh 1.152 jam pelajaran per tahun. Tapi distribusi harinya—lima atau enam—diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan.
Pendekatan ini tidak hanya teknis, tapi juga filosofis. Dalam Lampiran II, dijelaskan prinsip adaptasi beban belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kemampuan sekolah. Bahkan pada satuan PAUD dan TK luar biasa, waktu belajar bisa disesuaikan secara individual. Ini menunjukkan bahwa kebijakan telah bergerak ke arah humanisme pendidikan, bukan sekadar struktur administratif.
Sikap ini ditegaskan oleh Prof. Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: “Lima hari boleh, enam hari boleh. Semua wewenangnya pada Pemerintah Daerah, yang dihitung lama satu minggu” (Liputan6.com, 9 Juli 2025). Pandangan ini menunjukkan kelas kepemimpinan yang memahami konteks, memberi kepercayaan kepada daerah, dan tidak terjebak pada skema tunggal.
Dalam dunia kebijakan yang sering tergoda menyamaratakan semuanya, keberanian untuk merawat keragaman dalam koridor regulasi adalah bentuk kearifan. Regulasi ini layak diapresiasi karena tidak hanya memberi kelonggaran, tetapi juga mendorong tumbuhnya dialog antara pusat dan daerah, antara aturan dan kenyataan.
Belajar dari MI NU Mathalibul Huda
Fullday school sering disalahpahami sebagai kebijakan yang sekadar memadatkan hari belajar dari enam menjadi lima hari. Padahal, esensi model ini bukan terletak pada jumlah harinya, melainkan pada kualitas pembelajaran yang utuh, terstruktur, dan bermakna. Yang membedakan adalah pendekatan mutu, bukan waktu.
Salah satu contoh inspiratif datang dari MI NU Mathalibul Huda Mlonggo Jepara. Madrasah ini berada di bawah naungan Yayasan Mathalibul Huda, sebuah lembaga pendidikan berbasis pesantren yang berdiri sejak 1935. Dipimpin oleh Drs. H. Sugiwanto, MM sebagai Ketua Yayasan, lembaga ini menaungi tiga jenjang pendidikan: MI, MTs, dan MA dengan total lebih dari 3.200 siswa.
Untuk jenjang MI saja, jumlah siswa di MI NU Mathalibul Huda mencapai lebih dari 1.200 anak, terbagi dalam 38 rombongan belajar (rombel) dari kelas 1 hingga 6, dengan rata-rata 32 siswa per kelas. Tahun ini, antusiasme masyarakat tercermin dari dibukanya 7 rombel khusus kelas 1, sementara pendaftaran siswa baru bahkan sudah dimulai satu tahun sebelumnya—bukti nyata kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang ditawarkan madrasah ini.
Yang menarik, meskipun MI NU Mathalibul Huda menerapkan model fullday selama enam hari dalam seminggu, sistem ini justru tidak dianggap sebagai beban oleh siswa atau orang tua. Sebaliknya, model ini mendapat sambutan hangat karena berhasil memadukan tiga pilar utama yang dicari keluarga muslim: penguatan ilmu umum, pendalaman agama, dan pembentukan akhlak mulia dalam satu lingkungan belajar yang terintegrasi.
Menurut Prof. Dr. H. Mustaqim, M.Pd., Ketua Bidang Akademik dan SDM Yayasan, sistem ini “merespons tuntutan dan mewadahi keinginan masyarakat” secara utuh. Dalam pandangan beliau, fullday bukanlah sekadar format waktu, tapi visi untuk mencetak lulusan berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman.
Fasilitas belajar pun menjadi daya dukung signifikan. Setiap ruang kelas dilengkapi AC dan toilet di dalam ruang. Suasana bersih, tertib, dan rapi menjadikan pengalaman belajar di madrasah ini terasa nyaman dan bermartabat—jauh dari kesan “pinggiran” yang sering dilekatkan pada lembaga pendidikan berbasis pesantren.
Kurikulumnya menggabungkan standar nasional Kementerian Agama dengan kekhasan pesantren: tahfidz, tartil, tahsin, kitab kuning, pembiasaan adab santri, serta ibadah harian. Semua kegiatan diatur dalam jadwal harian yang menyatu antara intelektual dan spiritual.
Dengan pendekatan ini, fullday school di MI NU Mathalibul Huda bukan sekadar program waktu panjang. Ia menjadi wadah pembentukan karakter yang menyeluruh, tanpa kehilangan akar sosial dan budaya masyarakat sekitar.
Model ini membuktikan bahwa fullday school bisa dijalankan secara kontekstual dan adaptif. Ia tidak meminggirkan istirahat anak, tidak menggerus nilai lokal, dan tetap selaras dengan visi yayasan serta tradisi pesantren. Fullday menjadi pemaksimalan peluang, bukan pemampatan waktu.
Maka, perdebatan tentang lima atau enam hari sebaiknya diarahkan pada substansi pendidikan: apakah sistem yang diterapkan mampu membangun manusia utuh? MI NU Mathalibul Huda menjawabnya dengan praktik, bukan sekadar teori.
Menuju Fullday yang Relevan dan Membumi
Perdebatan tentang fullday school tidak semestinya dikunci pada perbedaan antara lima atau enam hari belajar. Esensinya bukan soal durasi, tetapi bagaimana waktu belajar digunakan untuk membentuk karakter, memperdalam ilmu, dan menumbuhkan nilai-nilai kehidupan. Madrasah seperti MI NU Mathalibul Huda Mlonggo Jepara telah membuktikan bahwa model fullday bisa berjalan secara kontekstual, dengan dukungan masyarakat, fasilitas yang layak, dan integrasi kurikulum keislaman yang kuat.
Kebijakan nasional memang memerlukan batasan dan kerangka regulasi. Namun pelaksanaannya harus memberi ruang bagi keragaman sosial dan budaya lokal. Dalam hal ini, pernyataan Prof. Abdul Mu’ti bahwa “lima hari boleh, enam hari boleh” bukan sekadar klarifikasi administratif, melainkan penegasan bahwa pendidikan yang baik lahir dari pendekatan yang dekat dengan realitas peserta didik dan komunitasnya.
Kita patut mengapresiasi madrasah yang mampu mengelola fullday secara adaptif—bukan hanya mengatur waktu, tetapi menciptakan atmosfer belajar yang menyenangkan, bermakna, dan membumi. Madrasah seperti ini tidak hanya menyesuaikan regulasi, tetapi menanamkan visi yang menyatu antara ilmu, akhlak, dan semangat kebangsaan.
Maka, praktik baik seperti di MI NU Mathalibul Huda layak menjadi rujukan nasional. Ia membuktikan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya dibentuk oleh aturan yang baku, tetapi oleh jiwa kelembagaan yang hidup dan berakar pada nilai. Di situlah madrasah tampil sebagai pelopor perubahan—dengan cara yang tenang, kontekstual, dan berkarakter. Wallāhu a‘lam biṣ-ṣawāb.
Dr. A. Umar, MA (Dosen FITK UIN Walisongo Semarang)