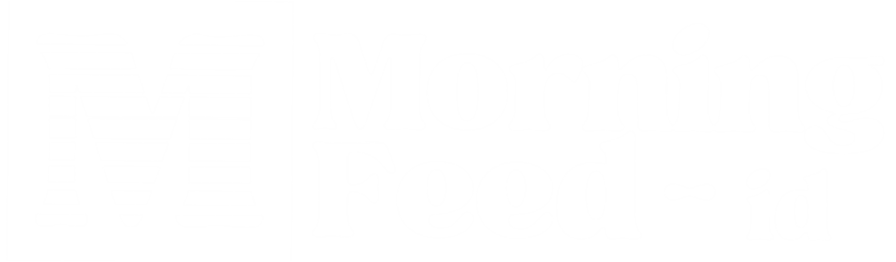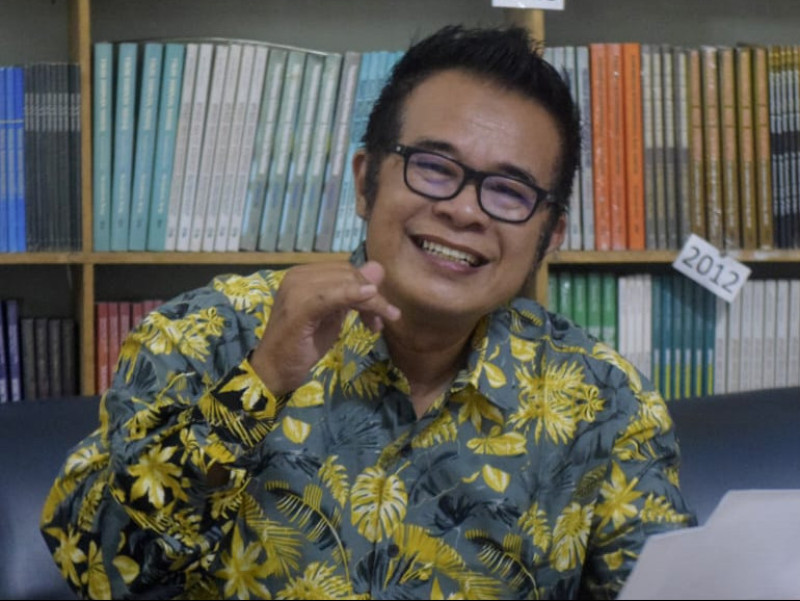Bayangkan sebuah kelas sastra di sekolah menengah: dinding-dindingnya dipenuhi poster tentang unsur intrinsik puisi dan novel, sementara siswa duduk rapi, menulis jawaban dari soal pilihan ganda tentang majas, rima, atau struktur cerita. Tidak ada diskusi tentang perasaan yang ditimbulkan sebuah puisi, tidak ada dialog tentang penderitaan tokoh dalam cerpen, dan hampir tidak ada ruang untuk merasakan makna di balik kata-kata. Dalam suasana kering itu, sastra kehilangan jiwanya; ia menjadi teks mati yang hanya berfungsi untuk diuji, dinilai, dan dilaporkan.
Fenomena ini bukan sekadar ilustrasi hiperbolik. Ia mencerminkan kondisi nyata pendidikan sastra formal di banyak sekolah di Indonesia, di mana kurikulum menekankan penilaian kuantitatif ketimbang pengalaman estetis dan transformasi batin siswa. Sastra, yang seharusnya menjadi ruang imajinasi, refleksi, dan empati, justru berubah menjadi sekadar materi kognitif yang dikupas secara mekanis.
Tesis esai ini menegaskan bahwa kurikulum sastra yang terlalu menekankan pengukuran formal justru menghilangkan jiwa sastra. Untuk membangkitkan kembali makna pendidikan sastra, diperlukan kurikulum yang hidup: yang memberi ruang bagi imajinasi, refleksi, dan kemanusiaan. Dengan kurikulum semacam ini, sastra tidak lagi sekadar teks mati, melainkan jendela untuk memahami diri, masyarakat, dan dunia secara lebih luas.
Kritik atas Kurikulum Sastra Formal
Salah satu masalah utama dalam kurikulum sastra formal adalah reduksi sastra menjadi materi kognitif semata. Siswa diajarkan untuk menghafal definisi majas, mengenali alur cerita, dan mengidentifikasi tokoh utama serta konflik. Pendekatan ini memandang sastra seperti objek laboratorium yang bisa dibedah, dianalisis, dan dinilai secara objektif, tetapi jarang dihayati sebagai pengalaman estetis yang hidup.
Misalnya, puisi yang seharusnya menjadi medium pengalaman batin, diajarkan layaknya anatomi. Siswa mempelajari majas dan rima, menandai bait demi bait, lalu diminta menjawab soal pilihan ganda atau membuat ringkasan. Tidak ada ruang bagi siswa untuk merasakan irama kata, menghayati metafora, atau menyelami emosi yang tersirat di balik teks. Proses ini menghasilkan persepsi bahwa sastra hanyalah “bahan ujian,” bukan sumber kehidupan batin yang mengasah kepekaan, empati, dan imajinasi.
Pendekatan semacam ini berlawanan dengan pemikiran Paulo Freire, yang menekankan pendidikan sebagai proses membebaskan dan memberdayakan. Freire menyoroti bagaimana pendidikan yang kaku, yang ia sebut banking education, membekukan kreativitas dan kemampuan kritis peserta didik karena menempatkan siswa sebagai penerima pasif pengetahuan, bukan subjek yang aktif mengeksplorasi makna (Freire, Pedagogy of the Oppressed, New York: Continuum, 2005:72). Kurikulum sastra yang menekankan hafalan dan analisis struktural dengan cara mekanis menyerupai banking education, sehingga jiwa sastra tidak berkembang.
Di Indonesia, efeknya sangat nyata. Siswa mampu menjawab soal-soal tentang unsur intrinsik puisi atau alur novel, namun jarang bisa menjelaskan bagaimana sastra membentuk rasa kemanusiaan, kesadaran sosial, atau pemahaman tentang penderitaan orang lain. Dengan demikian, kurikulum formal justru menjadi penghalang transformasi batin yang seharusnya menjadi inti pembelajaran sastra.
Lebih jauh lagi, fokus yang terlalu kuat pada aspek formalistik sastra mendorong pembelajaran yang statis dan kaku. Analisis teks menjadi tujuan akhir, bukan sarana untuk membangkitkan pengalaman batin dan refleksi kritis. Siswa belajar untuk menjawab soal, bukan untuk merasakan. Dalam konteks ini, sastra kehilangan potensinya sebagai medium pembebasan, yang semestinya mampu menumbuhkan kesadaran kritis terhadap diri dan masyarakat.
Orientasi Hasil (Nilai) vs Proses (Jiwa)
Masalah mendasar lain adalah orientasi pendidikan sastra yang lebih menekankan hasil, angka, nilai, dan sertifikat, ketimbang proses internal siswa. Orientasi nilai menuntut siswa untuk menghafal, menyusun laporan analisis, atau sekadar menjawab soal agar lulus, tanpa memperhatikan pengalaman estetis dan pertumbuhan pribadi.
Sebaliknya, orientasi proses menekankan pengalaman membaca dengan rasa, menulis kreatif, berdiskusi tentang makna hidup, dan merenungkan hubungan teks dengan realitas sosial maupun batin pribadi. Ketika proses ini diabaikan, siswa mungkin dapat menjawab soal analisis novel Laskar Pelangi dengan tepat, misalnya menjelaskan tokoh Ikal, alur cerita, atau konflik sosial; namun gagal menangkap pesan moral dan spiritual perjuangan, solidaritas, serta semangat hidup yang terkandung di dalamnya.
Freire menegaskan bahwa pendidikan yang membebaskan menekankan praksis: refleksi yang dipadukan dengan tindakan nyata (Freire, 2005:79). Dalam konteks sastra, praksis ini berarti membaca dan menulis tidak hanya untuk memenuhi kriteria akademis, tetapi juga untuk membentuk kepekaan estetis, empati, dan pemahaman tentang kemanusiaan. Orientasi hasil, sebaliknya, menghasilkan siswa yang “melek teks” tetapi “buta jiwa,” yang menghafal definisi tetapi tidak menyentuh hidup batin atau dunia sosial.
Contoh nyata terlihat pada praktik kurikulum sastra di sekolah menengah di Indonesia. Siswa sering diminta membuat analisis novel atau puisi dalam bentuk tabel: tokoh, alur, latar, amanat. Proses ini bersifat mekanis dan formalistik. Tidak ada sesi membaca puisi secara lantang untuk merasakan irama kata, tidak ada kegiatan menulis puisi berdasarkan pengalaman pribadi, dan tidak ada ruang bagi diskusi mendalam yang mengaitkan teks dengan kehidupan nyata. Akibatnya, sastra berubah menjadi kumpulan definisi dan formula yang kaku.
Hilangnya Dimensi Empati dan Spiritualitas
Sastra sejatinya adalah jalan untuk mengasah empati. Melalui narasi, siswa dapat merasakan penderitaan orang lain, memahami kompleksitas kehidupan, dan merenungkan misteri eksistensi manusia. Martha Nussbaum menekankan bahwa pendidikan sastra berperan penting dalam menumbuhkan empati, yang merupakan dasar demokrasi dan kemanusiaan (Nussbaum, Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities, Princeton: Princeton University Press, 2010:35).
Namun, kurikulum formal seringkali mengabaikan dimensi ini karena tidak bisa diukur dengan tes objektif. Misalnya, cerpen tentang kemiskinan atau ketidakadilan sosial hanya dipakai untuk mengidentifikasi tokoh utama, konflik, atau alur cerita, bukan untuk merasakan penderitaan sosial yang dialami tokoh. Analisis semacam ini memisahkan siswa dari pengalaman batin yang seharusnya mereka alami, sehingga sastra kehilangan potensinya sebagai alat transformasi emosional dan spiritual.
Di sisi lain, pendidikan yang mengintegrasikan dimensi empati dan spiritualitas mendorong siswa untuk menulis jurnal reflektif, berdiskusi tentang nilai-nilai kemanusiaan dalam teks, atau bahkan mengekspresikan pengalaman membaca melalui karya kreatif. Dengan demikian, sastra menjadi medium pengembangan batin, bukan sekadar objek akademik. Hilangnya dimensi ini berarti pembelajaran sastra tidak hanya membekukan teks, tetapi juga membatasi pertumbuhan moral dan spiritual siswa.
Selain itu, pengalaman membaca yang hidup juga mendorong siswa menumbuhkan kesadaran diri. Siswa yang dihadapkan pada pengalaman batin tokoh dalam novel atau puisi akan mulai merefleksikan diri mereka sendiri: nilai-nilai, kekurangan, ambisi, dan empati. Tanpa kurikulum yang memungkinkan refleksi ini, sastra kehilangan peran pentingnya dalam pengembangan karakter dan spiritual.
Peran Guru dan Komunitas dalam Membebaskan Sastra
Guru memegang peran strategis dalam menentukan apakah sastra tetap menjadi teks mati atau menjadi medium transformasi batin. Guru yang hanya menekankan analisis formalistik tanpa memberikan ruang ekspresi kreatif cenderung melahirkan generasi “melek teks tapi buta jiwa.” Sebaliknya, guru yang mendorong eksplorasi imajinatif, diskusi kritis, dan refleksi pribadi membantu siswa merasakan kehidupan batin dalam teks.
Selain guru, komunitas belajar juga dapat memainkan peran penting. Di luar kelas formal, komunitas sastra—seperti klub menulis, forum baca puisi, atau kelompok diskusi literasi—menawarkan ruang bagi siswa untuk mengekspresikan pemahaman dan perasaan mereka terhadap teks. Dalam konteks Indonesia, komunitas seperti Komunitas Katakata (Sumatera Utara), Seni Kuflet (Sumatera Barat), Natuna Sastra (Kepulauan Riau), Tatkala (di Bali), Literasi Perpustakaan Kota Palu (Sulawesi Tengah), Rumah Kreatif Wadas Kelir, Komunitas Pesantren Mahasiswa An Najah, Lembaga Kajian Nusantara Raya (di Purwokerto), dan seterusnya, menunjukkan bahwa pembelajaran sastra yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis pengalaman hidup mampu membangkitkan kembali jiwa sastra yang hilang. Siswa tidak hanya membaca dan menulis, tetapi juga berdiskusi, merefleksikan, dan mengaitkan teks dengan pengalaman spiritual dan sosial mereka.
Pengalaman ini menegaskan bahwa sastra bukan sekadar objek akademik; ia adalah medium dialog batin, sarana ekspresi kreatif, dan jendela untuk memahami realitas sosial. Kurikulum formal yang membatasi kegiatan ini hanya pada aspek kognitif gagal mengintegrasikan dimensi sosial, emosional, dan spiritual.
Sastra sebagai Teks Hidup: Paradigma Kurikulum Alternatif
Muncul pertanyaan: bagaimana kurikulum sastra dapat diubah agar menjadi teks hidup? Pertama, kurikulum harus menekankan pengalaman membaca dan menulis sebagai proses reflektif. Setiap teks sastra perlu dibaca tidak hanya untuk memahami alur atau tokoh, tetapi juga untuk merasakan emosi, menangkap pesan moral, dan mengeksplorasi makna simbolik yang terkandung.
Kedua, penilaian perlu berorientasi pada proses, bukan sekadar hasil. Misalnya, guru dapat menilai refleksi pribadi siswa setelah membaca puisi, karya kreatif yang mereka tulis, atau diskusi kelompok tentang isu-isu sosial yang relevan dengan teks. Dengan cara ini, nilai tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan indikator partisipasi dalam proses pembelajaran batin.
Ketiga, penguatan komunitas belajar di luar sekolah dapat memberikan dimensi pengalaman yang lebih luas. Melalui workshop, diskusi terbuka, atau pertunjukan kreatif, siswa belajar mengaitkan teks dengan kehidupan nyata. Interaksi sosial dan pengalaman kolektif ini menumbuhkan empati, kreativitas, dan kesadaran spiritual, yang semuanya tidak bisa dicapai melalui tes formal semata.
Paradigma kurikulum semacam ini sejalan dengan gagasan Nussbaum tentang pendidikan humanistik, yang menekankan pengembangan kemampuan kritis, empati, dan rasa tanggung jawab sosial. Sastra menjadi medium untuk menumbuhkan kesadaran global dan kemanusiaan, bukan sekadar alat evaluasi akademik.
Implikasi Sosial dan Spiritual
Mengembalikan sastra sebagai teks hidup memiliki implikasi yang luas. Secara sosial, siswa yang mengalami pembelajaran sastra yang hidup cenderung lebih peka terhadap ketidakadilan, lebih mampu memahami perspektif orang lain, dan lebih terbuka terhadap dialog kemanusiaan. Secara spiritual, siswa belajar merenungkan eksistensi, moralitas, dan makna hidup melalui teks. Puisi atau cerpen menjadi sarana meditasi batin, tempat untuk mengekspresikan emosi dan menumbuhkan kesadaran diri.
Sebaliknya, kurikulum yang membekukan sastra memicu homogenisasi pengalaman. Siswa diajarkan cara “melihat” teks secara sama, memikirkan jawaban yang sama, dan menilai realitas dengan standar kaku. Dalam jangka panjang, pengalaman ini dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis, empati, dan sensitivitas spiritual, sehingga lahirlah generasi yang mampu menguasai bentuk, tetapi kehilangan isi.
Lebih jauh, hilangnya dimensi spiritual dan sosial dalam pendidikan sastra dapat berimplikasi pada kemerosotan kualitas literasi kritis dalam masyarakat. Sastra yang mati membatasi kemampuan individu untuk memahami nilai, budaya, dan etika, serta membatasi kemampuan mereka untuk menilai realitas sosial secara mendalam. Dengan demikian, masalah kurikulum sastra bukan sekadar persoalan akademik, melainkan persoalan kemanusiaan dan spiritual.
Refleksi dan Rekomendasi
Refleksi atas fenomena ini menegaskan perlunya reformasi kurikulum yang mendasar. Pertama, pendidikan sastra harus melihat siswa sebagai subjek aktif yang terlibat secara batiniah, bukan objek pasif yang dikondisikan untuk menghafal. Kedua, penekanan pada nilai kuantitatif perlu dikurangi, diganti dengan penilaian proses yang menekankan pengalaman estetik, refleksi kritis, dan ekspresi kreatif. Ketiga, integrasi komunitas belajar dan media kreatif perlu didorong agar pembelajaran tidak terbatas pada kelas formal.
Implementasi perubahan ini menuntut komitmen guru, kepala sekolah, pembuat kebijakan, dan komunitas literasi. Guru perlu dilatih untuk mengajar sastra dengan pendekatan reflektif, partisipatif, dan kontekstual. Kurikulum harus memberi ruang untuk kegiatan kreatif, dialog sosial, dan eksplorasi batin. Komunitas belajar dapat menjadi mitra strategis dalam menyediakan pengalaman praktis dan mendalam.
Sastra yang hanya diajarkan sebagai teks formal akan kehilangan jiwanya. Kurikulum yang membekukan sastra menjadi teks mati menutup ruang bagi pengalaman batin, refleksi kritis, dan transformasi spiritual siswa. Pendidikan sastra yang hidup menuntut integrasi pengalaman membaca, menulis kreatif, refleksi batin, dan interaksi sosial. Dengan pendekatan semacam ini, sastra kembali menjadi medium transformasi kemanusiaan: bukan sekadar teks untuk diuji, tetapi jendela untuk memahami diri, masyarakat, dan dunia.
Dalam konteks Indonesia, reformasi kurikulum ini bukan sekadar isu pedagogis, tetapi juga isu kemanusiaan dan spiritual. Melalui pendidikan sastra yang hidup, generasi muda dapat menumbuhkan empati, kepekaan sosial, dan kesadaran spiritual: nilai-nilai yang krusial untuk membangun masyarakat yang beradab, kritis, dan humanis. Sebaliknya, kurikulum yang membekukan sastra menutup peluang ini, menjadikan generasi melek teks tetapi kehilangan jiwa. Reformasi kurikulum yang menghidupkan kembali sastra bukan pilihan, melainkan kebutuhan untuk memastikan bahwa sastra tetap menjadi medium hidup yang membawa manusia dari pemahaman kognitif ke pengalaman batin, dari teks mati ke jiwa yang hidup.***
Abdul Wachid B.S. (Penulis adalah penyair, Guru Besar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Ketua Lembaga Kajian Nusantara Raya (LK Nura) di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto)