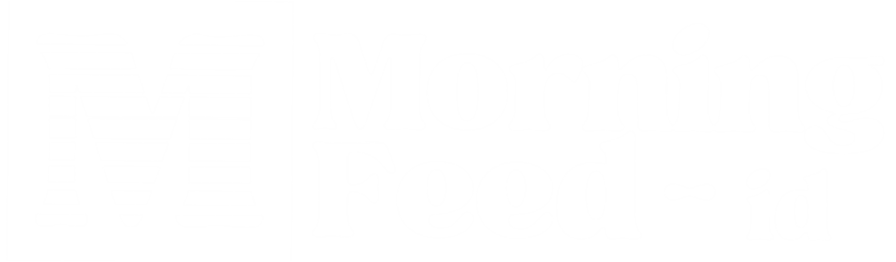Anselmus Dore Woho Atasoge (Staf Pengajar pada Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende)
Insiden perusakan rumah doa Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) di Padang, Sumatera Barat, pada 27 Juli 2025, bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan sebuah tragedi spiritual yang mengoyak kesadaran kolektif kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keberagaman. Ketika anak-anak berlarian dalam kepanikan dan kaca rumah doa pecah oleh amarah massa, kita menyaksikan bukan hanya keretakan fisik, tetapi juga retaknya relasi sosial dan spiritual antarumat beragama.
Dalam konteks ini, pernyataan Menteri Agama RI Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar (dalam Tempo.co., 06/08/2025) tentang perlunya pendekatan berbasis kurikulum cinta menjadi tawaran visioner yang melampaui sekadar kebijakan administratif. Ia mengusulkan agar pendidikan agama tidak lagi berpusat pada principle of negation (penekanan pada perbedaan) melainkan beralih ke principle of identity, yaitu pengakuan atas kesamaan sebagai sesama anak bangsa dan sesama makhluk ciptaan. Kurikulum ini dirancang untuk menanamkan empati, penghargaan atas martabat manusia, dan semangat belas kasih sebagai prinsip hidup beragama, bukan sekadar pengetahuan formal.
Gagasan ini sejalan dengan pandangan Islam tentang dialog antaragama sebagaimana diuraikan oleh Dr. Salih bin Humaid melalui karyanya “The Islamic View of Dialogue with The Other”. Dalam Islam, dialog bukan sekadar alat diplomasi, melainkan ekspresi dari nilai-nilai tauhid yang mengakui keragaman sebagai kehendak ilahi. QS. Al-Hujurat: 13 menegaskan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, bukan saling meniadakan. Dialog dalam Islam bertujuan menyampaikan pesan dengan hikmah, membangun koeksistensi damai, dan menolak kekerasan dalam urusan keyakinan. Etika dialog menuntut kejujuran intelektual, penghormatan terhadap keyakinan lain, dan penolakan terhadap debat yang merendahkan.
Dalam konteks ini, Nasaruddin Umar mengedepankan kembali konsep ukhuwah makhlukiyah untuk memperluas cakrawala spiritual kita. Ukhuwah makhlukiyah adalah konsep persaudaraan yang melampaui batas manusia dan agama, mencakup seluruh makhluk ciptaan Tuhan (manusia, hewan, tumbuhan, bahkan unsur alam semesta). Dalam pandangan Nasaruddin Umar dan tokoh lain seperti Habib Ja’far, ukhuwah ini mengajarkan bahwa semua makhluk adalah bagian dari ciptaan Ilahi dan karenanya layak dihormati dan dicintai.
Habib Husein bin Ja’far Al Hadar, seorang pendakwah, penulis, dan intelektual muda Islam Indonesia bahkan menyebut bahwa mencintai makhluk ciptaan Tuhan adalah bentuk penghormatan terhadap Sang Pencipta, seperti menghargai lukisan karena menghormati pelukisnya. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamin), bukan hanya untuk manusia, tapi untuk semesta.
Konsep ini mengajak kita untuk memperluas cakrawala persaudaraan: dari sesama manusia (ukhuwah basyariyah), sesama bangsa (ukhuwah wathaniyah), sesama umat beriman (ukhuwah islamiyah), hingga sesama makhluk ciptaan Tuhan. Jika direnungkan lebih dalam maka dapat dikatakan bahwa konsep ini merupakan sebuah spiritualitas yang menyatukan cinta, ekologi, dan etika dalam satu napas.
Dalam tradisi Kristiani, ini sejalan dengan spiritualitas Fransiskan yang melihat alam semesta sebagai saudara dan saudari dalam rumah bersama Allah. Re-sakralisasi alam semesta, sebagaimana diserukan Nasaruddin, adalah panggilan lintas iman untuk memulihkan hubungan kita dengan ciptaan, bukan sebagai objek eksploitasi, tetapi sebagai subjek relasional yang mengundang kita pada kontemplasi dan tanggung jawab ekologis.
Karena itu, kurikulum cinta bukan sekadar silabus, melainkan cara hidup. Ia mengajarkan bahwa empati lebih penting daripada dogma, bahwa belas kasih lebih kuat daripada klaim kebenaran tunggal. Dalam dialog antaragama, kurikulum ini menjadi jembatan spiritual yang menghubungkan tradisi, bukan untuk menyeragamkan, tetapi untuk saling memperkaya.
Ketika rumah doa dirusak, bukan hanya bangunan yang runtuh, tetapi juga harapan akan masa depan yang damai. Namun, jika kurikulum cinta dan dialog lintas iman dijadikan fondasi, maka dari puing-puing itu bisa tumbuh taman pengertian, tempat di mana anak-anak dari berbagai agama bisa bermain tanpa takut, dan orang dewasa bisa berdoa tanpa curiga.
Indonesia tidak kekurangan undang-undang, tetapi mungkin kekurangan kelembutan. Dialog antaragama yang berakar pada cinta dan persaudaraan kosmik adalah jalan transformasi dari trauma menuju rekonsiliasi. Kita tidak hanya membutuhkan hukum yang mengatur, tetapi hati yang menyentuh. Dan mungkin, dalam keheningan rumah doa yang telah dirusak, suara Tuhan masih berbisik: “Cintailah sesamamu, karena mereka adalah wajah-Ku yang lain.”*
Anselmus Dore Woho Atasoge (Staf Pengajar pada Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende)