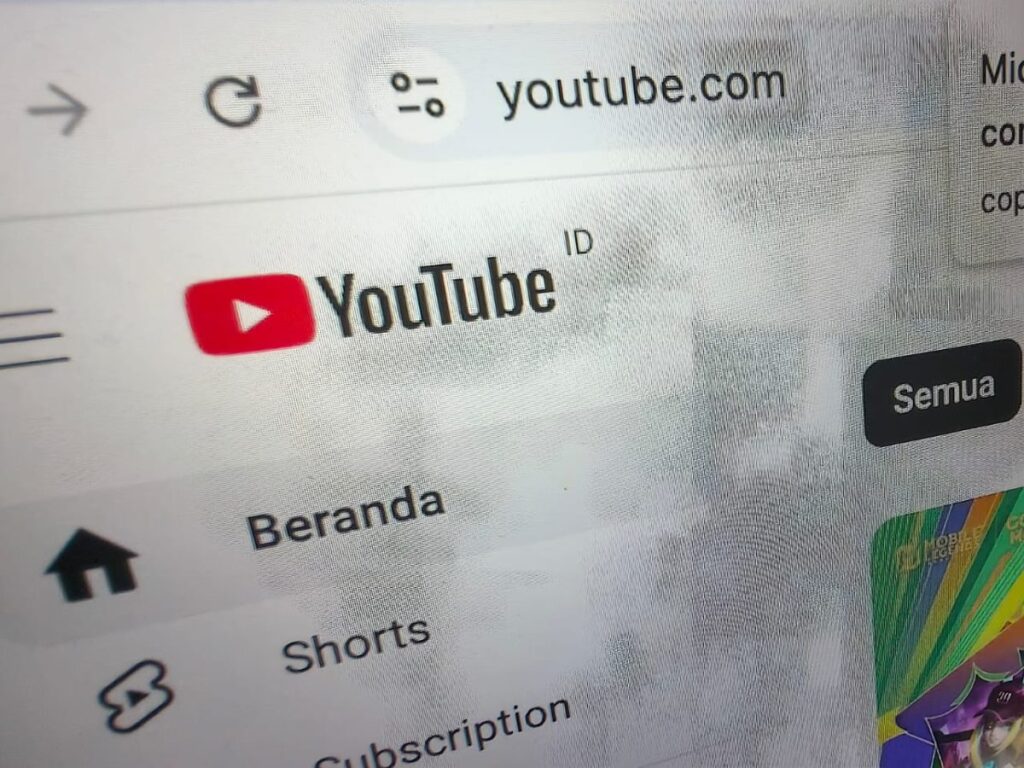Pemerintah Australia resmi mencabut pengecualian untuk YouTube dalam kebijakan pelarangan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun, sebuah langkah yang menuai perdebatan tajam di tengah masyarakat, terutama dari kalangan Gen Z yang tumbuh besar bersama platform tersebut.
Langkah ini merupakan bagian dari larangan nasional media sosial untuk remaja yang akan mulai diberlakukan pada Desember 2025, menyasar semua platform utama seperti Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, dan kini YouTube.
Kebijakan ini mewajibkan platform digital untuk mengambil “langkah-langkah wajar” dalam mencegah anak di bawah 16 tahun memiliki akun, dengan sanksi denda hingga AUD 49,5 juta sekitar (Rp504,9 miliar) jika terbukti lalai.
“Saya menyatakan waktunya sudah habis,” ujar Perdana Menteri Anthony Albanese, seperti dilansir dari Reuters. “Kami ingin para orang tua tahu bahwa pemerintah berada di pihak mereka.”
Namun bagi remaja seperti Leo Puglisi (17), keputusan ini terasa seperti tamparan bagi kebebasan berekspresi dan ruang belajar generasi muda. Puglisi adalah pendiri 6 News Australia, saluran berita independen yang ia mulai di YouTube saat berusia 11 tahun. Di usia 14, ia sudah mewawancarai Perdana Menteri Australia.
“YouTube adalah satu-satunya tempat yang memungkinkan saya memulai semua ini,” ujar Puglisi kepada abc.net.au. “Bagi banyak anak muda, platform ini bukan sekadar hiburan, tapi ruang untuk mengekspresikan kreativitas dan minat mereka.”
YouTube telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan Gen Z. Data pemerintah menunjukkan hampir 75% anak berusia 13–15 tahun di Australia menggunakan YouTube, menjadikannya platform paling populer di kelompok usia ini, bahkan mengungguli TikTok dan Instagram.
Namun ironisnya, justru karena tingkat penggunaan yang tinggi dan tingkat paparan konten berbahaya mencapai 37%, pemerintah kini memasukkannya ke dalam daftar larangan.
Bagi remaja seperti Callum (18 tahun), YouTube bukan hanya tempat nostalgia. Ia tumbuh menonton video Minecraft sejak usia enam tahun, namun juga mengakui pernah hampir terjebak dalam konten ekstrem kanan akibat algoritma yang terus mendorong konten serupa.
“Saya nyaris masuk ke lubang ekstrem kanan. Saya mulai bertanya-tanya dan untungnya mendapat teguran dari orang-orang di sekitar saya,” ungkapnya.
Callum mendukung pelarangan YouTube sebagai bentuk perlindungan, tetapi tetap mengakui bahwa ini berarti hilangnya akses terhadap budaya digital dan komunitas online.
Tak sedikit remaja lainnya yang merasa kebijakan ini tidak realistis dan sulit ditegakkan secara merata. Abby (13 tahun) mengaku media sosial bisa membuat stres, tetapi juga penting sebagai sarana berkomunikasi.
“Kalau tidak semua orang dilarang, akan timbul rasa terasing. Anak-anak bisa merasa dikucilkan secara sosial,” ujarnya.
Audrey (11 tahun) menambahkan, ia dan teman-temannya sudah tahu cara mengakali sistem verifikasi umur menggunakan data palsu atau masker wajah untuk menghindari deteksi.
YouTube awalnya dikecualikan dari larangan karena alasan edukatif dan sering digunakan di ruang kelas. Namun setelah desakan dari Komisioner eSafety Julie Inman Grant, pemerintah berbalik arah.
Pihak YouTube menyatakan keberatan atas klasifikasi tersebut. “YouTube adalah platform berbagi video, bukan media sosial,” kata juru bicara YouTube dalam pernyataan resmi. Mereka menyoroti bahwa YouTube berisi jutaan konten edukatif yang bermanfaat dan semakin banyak ditonton di layar televisi, bukan ponsel.
Namun, para pesaing seperti Meta, TikTok, dan Snapchat justru menyambut baik langkah ini, setelah sebelumnya memprotes perlakuan istimewa terhadap YouTube yang juga menggunakan algoritma dan interaksi sosial mirip dengan mereka.
Peneliti dari Monash University, Dr. Matthew Fyfield, menemukan bahwa meskipun YouTube sering dipakai untuk pembelajaran, algoritmanya dapat menjadi sumber gangguan besar.
“Platform ini dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Anak bisa lupa waktu hanya karena scroll tanpa henti,” ujarnya.
Sementara itu, organisasi seperti The Man Cave, yang membina kesehatan mental remaja laki-laki, menemukan bahwa 46% remaja merasa kehilangan koneksi sosial tanpa media sosial, dan 62% akan mencoba mencari celah untuk tetap mengaksesnya.