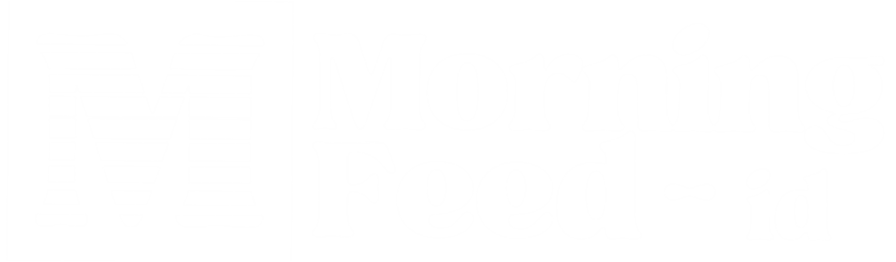A. Pendahuluan
Dalam wacana kesusastraan Nusantara kontemporer, perhatian kerap tertumpu pada pusat-pusat kebudayaan besar: Jakarta, Yogyakarta, Kuala Lumpur. Namun rentang puitik wilayah Melayu jauh lebih luas; ia merentang melintasi batas-batas negara dan pulau, termasuk Brunei Darussalam yang secara geografis menempati bagian utara Pulau Borneo (Kalimantan). Menempatkan penyair Brunei dalam dialog dengan tradisi perpuisian Indonesia bukanlah semata-retorika geografis: ini adalah upaya untuk membaca kembali kontinuitas budaya, bahasa, dan pengalaman puitik yang serumpun.
Argumen esai ini sederhana namun punya implikasi besar: H. MAR (Dr. Haji Mohd Ali bin Haji Radin), melalui antologi Gelora, bukan hanya figur penting dalam sastra Brunei; puisinya juga menampakkan resonansi estetika dan tematik yang membuatnya layak dibaca sebagai bagian dari ruang puitik Nusantara, sebuah ruang yang menegaskan persilangan bahasa Melayu dan Indonesia, pengalaman historis bersama, dan sensitivitas religio-spiritual yang serupa. Untuk mendukung klaim ini, esai akan menggabungkan analisis tekstual atas puisi-puisi terpilih dari Gelora, kajian konteks historis-kultural, dan perbandingan singkat dengan beberapa figur utama perpuisian Indonesia yang berdekatan dalam mood dan perhatian tematik.
Beberapa hal perlu ditegaskan sejak awal. Gelora diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei (Bandar Seri Begawan) sebagai cetakan pertama pada tahun 2011, cetakan kedua 2023, 84 + x halaman; buku ini memuat sekitar 80 judul puisi yang ditulis pada rentang tahun kurang lebih 1990–2009. Data penerbitan dan keterangan isi ini penting karena menunjukkan bahwa antologi tersebut bukan kumpulan fragmen belaka, melainkan hasil produksi panjang dan konsisten yang merekam perkembangan suara penyair selama hampir dua dekade.
Secara tematik, puisi-puisi dalam Gelora menampilkan dua gerak utama yang akan menjadi fokus analisis: (1) gejolak batin dan kegelisahan eksistensial, sering muncul dalam citra-citra berat dan kata-kata yang berkonotasi dramatis; dan (2) horison spiritual/doa, di mana penderitaan pribadi diarahkan menjadi bentuk penghayatan religius. Sebagai contoh yang merepresentasikan nada gelap sekaligus religius ini, sebuah fragmen yang membaca: “Langkahku mati/ di lorong gelap/ membakar gerak nafas/ garis-garis luka bersangkutan di tembok batu/ jatuh dipanas matahari/ kering/ layu/ diburu jejak bayang sendiri!” (2023:3). Kutipan ini memperlihatkan bagaimana teks H.MAR tak segan memanggil citra-citra ekstrem untuk menguji batas makna dan iman; fragmen ini juga memperlihatkan pilihan bahasa yang dekat dengan ekspresi puitik Nusantara yang reflektif dan kadang lugas dalam jujurnya.
B. Kedekatan Geografis dan Historis
Membicarakan puisi Brunei tanpa menyinggung konteks geografis dan historisnya berarti kehilangan fondasi utama yang menopang lahirnya suara puitik itu. Brunei Darussalam berdiri sebagai negara berdaulat sejak 1984, tetapi secara geografis ia merupakan bagian integral dari pulau Borneo (Kalimantan). Pulau ini bukanlah ruang terisolasi; sejak berabad-abad ia menjadi ladang pertemuan antara etnis Dayak, Melayu, Bugis, Jawa, dan komunitas perantau lain, serta menjadi arena pertemuan kolonialisme Belanda dan Inggris. Oleh sebab itu, suara penyair Brunei sesungguhnya juga merupakan gema dari sejarah panjang Nusantara yang melintasi batas negara modern.
A. Teeuw pernah mengingatkan bahwa sastra Indonesia modern lahir dan berkembang bukan dalam ruang hampa, tetapi dalam persilangan sejarah Nusantara yang panjang, di mana Melayu, Jawa, dan tradisi lokal lain saling memberi warna (Sastra Baru Indonesia, Jakarta: Nusa Indah, 1980). Pernyataan ini menegaskan bahwa membaca H.MAR sebagai penyair Brunei semata akan mereduksi kekayaan konteks yang membentuk puisinya. Ia lahir dari Borneo, sebuah pulau yang justru menjadi simbol persilangan sejarah Nusantara itu sendiri.
Sejarah Brunei sendiri memperlihatkan dinamika panjang hubungan dengan wilayah sekitarnya. Pada abad ke-14 dan 15, Kesultanan Brunei menjalin hubungan erat dengan Kesultanan Malaka. Sesudahnya, relasi politik dan budaya Brunei juga terkait dengan jalur perdagangan pesisir Kalimantan yang ramai oleh pedagang Bugis, Jawa, hingga Cina. Dalam konteks inilah, bahasa Melayu Brunei menjadi medium utama, yang belakangan berkembang paralel dengan bahasa Indonesia modern. Kedekatan linguistik inilah yang membuat pembaca Indonesia tidak kesulitan mengakses teks H.MAR.
Dengan latar semacam itu, muncul satu argumen penting: Brunei bukan entitas budaya yang terpisah dari Indonesia, melainkan bagian dari ekosistem budaya Kalimantan, Nusantara. Karena itu, menempatkan H.MAR dalam percaturan puisi Indonesia bukan sekadar anekdot lintas negara, tetapi langkah membaca kontinuitas sejarah.
Hal ini semakin jelas ketika menilik kembali tesis Azhar Ibrahim, seorang pengkaji sastra Melayu kontemporer, yang menulis: “The Malay world should not be confined by the artificial boundaries of the nation-state, for its cultural and intellectual traditions long predate colonial demarcations” (Contemporary Islamic Discourse in the Malay-Indonesian World: Critical Perspectives, Petaling Jaya: Strategic Information and Research Development Centre, 2013). (“Dunia Melayu tidak boleh dibatasi oleh batas negara-bangsa yang artifisial, karena tradisi kultural dan intelektualnya telah jauh mendahului garis demarkasi kolonial.”)
Maka, membaca H.MAR dari kacamata “Brunei sebagai negara” hanya separuh jalan; membaca H.MAR dari perspektif “Borneo–Nusantara” justru membuka seluruh lanskap kemungkinan. Ia adalah penyair Brunei, tetapi sekaligus penyair Kalimantan, penyair Melayu, penyair Nusantara.
C. Bahasa dan Tradisi Kepenyairan
Bahasa yang dipilih H.MAR dalam puisinya memperlihatkan kesinambungan antara tradisi Melayu klasik dan kepekaan modern yang sangat akrab bagi pembaca Indonesia. Sajak “Gelora”, ditulis tahun 1990, dimuat dalam kumpulan Gelora (2023:1) menjadi contoh jelas bagaimana bahasa Melayu Brunei tidak kehilangan resonansinya dengan tradisi perpuisian Indonesia.
GELORA
Pernah kumengutip sekuntum bunga
di taman larangan
keindahannya membakar
hatiku yang luka
lalu
kukucup bunganya
daunnya bergetar
kelopaknya luruh
bibirku pun basah!
1990
Dari kutipan ini tampak jelas kekuatan simbolik bunga yang diposisikan bukan sekadar objek estetis, melainkan lambang larangan, godaan, luka, sekaligus ekstasi. Bahasa yang sederhana, langsung, dan sarat simbol itu mencerminkan kesinambungan dengan tradisi Melayu klasik yang sering memanfaatkan metafora flora untuk menyampaikan pesan spiritual maupun erotik.
Namun, berbeda dari kecenderungan klasik yang sering berhenti pada ornamen, H.MAR menafsirkan kembali lambang bunga sebagai bagian dari pergulatan eksistensial. “Taman larangan” bisa dibaca sebagai simbol ruang tabu dalam kehidupan sosial atau spiritual. Tindakan “mengutip sekuntum bunga” lalu “kelopaknya luruh” menghadirkan pengalaman religius yang ambigu: di satu sisi menyentuh wilayah cinta dan keindahan, di sisi lain mengandung jejak dosa, luka, atau keterlarangan.
Bahasa dalam sajak ini sekaligus memperlihatkan apa yang disebut Goenawan Mohamad sebagai tegangan antara doa yang diwarisi dan kegelisahan yang dihayati (Kesusastraan dan Kekuasaan, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993). Tegangan inilah yang juga menjiwai puisi Indonesia modern, misalnya dalam karya Abdul Hadi W.M. yang banyak mengolah simbol cinta mistik, atau dalam puisi D. Zawawi Imron yang menghubungkan kerinduan spiritual dengan pengalaman keseharian.
Dari aspek tradisi bahasa, H.MAR menulis dalam bahasa Melayu Brunei yang serumpun dengan bahasa Indonesia. Menurut Anton M. Moeliono, Bahasa Melayu merupakan lingua franca di kepulauan Nusantara, yang bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi lintas etnis, tetapi juga menjadi wadah bagi ekspresi estetis dan intelektual (Perkembangan Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1986). Karena itu, pembaca Indonesia tak merasakan jarak bahasa saat membaca sajak H.MAR. Yang terasa justru kedekatan rasa, bahkan seolah puisinya lahir dari rahim yang sama dengan puisi Indonesia kontemporer.
Dalam kaitan ini, Azhar Ibrahim menekankan bahwa tradisi intelektual dan kultural Melayu-Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai warisan, tetapi juga sebagai wacana hidup yang terus-menerus ditafsirkan ulang oleh generasi penyair, cendekia, dan pemikirnya (Ibid.). Pandangan ini memperkuat posisi H.MAR sebagai bagian dari dinamika wacana bersama, bukan sekadar penyair lokal Brunei.
Maka, “Gelora” menegaskan bahwa tradisi kepenyairan H.MAR bukanlah entitas yang terpisah dari Indonesia. Justru sebaliknya, ia berdiri di dalam jaringan tradisi puitik Nusantara, tradisi yang hidup dari dialektika antara akar lokal dan horizon global, antara doa dan kegelisahan, antara larangan dan cinta.
D. Posisi H.MAR dalam Sastra Brunei: Representasi Simbol Rumah
Dalam perkembangan sastra Brunei modern, sejumlah penyair telah tampil sejak dekade 1970-an dan 1980-an. Shukri Zain, misalnya, dikenal sebagai salah satu perintis puisi modern Brunei yang banyak mengeksplorasi tema perjuangan, religiositas, dan identitas kebangsaan. Puisinya sering menekankan aspek didaktis dengan gaya retoris yang kuat. Di sisi lain, Norsiah Gapar mengekspresikan pengalaman perempuan, keintiman, dan ruang domestik sebagai representasi suara femininitas dalam sastra Brunei. Muslim Burmat serta Zefri Ariff, yang semasa dengan H.MAR, lebih banyak menggarap simbol-simbol alam, sejarah, dan kebudayaan Melayu Brunei dengan gaya yang puitis sekaligus reflektif.
Dalam konteks inilah H.MAR menampilkan ciri khasnya. Ia tidak menekankan retorika politik kebangsaan sebagaimana Shukri Zain, dan tidak pula berfokus secara khusus pada suara femininitas seperti Norsiah Gapar. H.MAR menghadirkan gaya yang lebih intim dan eksistensial, dengan menjadikan ruang privat, yakni “rumah”, sebagai pusat simbolis bagi refleksi kehidupan personal dan komunal.
Puisi “Rumahku” (2023:16) menjadi representasi keterasingan penyair di dalam ruang privatnya:
RUMAHKU
Hujan telah turun. Dan bumi
pun basah. Tidak pula aku dengar suara orang bernyanyi.
Di luar jendela:
Aku lihat daun-daun luruh.
Hujan telah turun. Dan mengapa aku masih di dalam rumah!
1998
Rumah di sini tampak sebagai ruang keterbatasan. Kehadiran hujan, keheningan, dan daun luruh membangun atmosfer keterasingan. Berbeda dengan Muslim Burmat yang lebih menekankan alam Brunei sebagai lambang kontinuitas tradisi, H.MAR justru menempatkan alam sebagai cermin batin yang sunyi. Ini memperlihatkan pergeseran dari orientasi kolektif ke orientasi eksistensial.
Sebaliknya, puisi “Rumah Kita” (2023:11) menghadirkan rumah sebagai ruang komunal, tempat keluarga dan harapan bersemayam:
RUMAH KITA
Ada sebuah rumah kecil di atas bukit. Dan pintunya tertutup.
Ketika bulan mengambang penuh, rumah kecil itu hampir menyerupai sebuah istana kaca.
Dan lampunya berwarna kuning dan merah.
“Itu rumah kita?” kata kau pada isterimu.
Pada anak-anak, kauceritakan tentang keindahan alam apabila berada dalam rumah di atas bukit. Dan pagi hari anak-anakmu selalu menangis karena bermimpi tentang bulan telah menjadi matahari.
Padamu; isterimu sering berkata: “Kita memang mempunyai rumah, tapi tidak pernah memiliki warna-warna.”
1998
Di sini, rumah bertransformasi menjadi simbol kolektif, meskipun tetap menyimpan ironi. Sang istri menegaskan keterbatasan.
Dibandingkan dengan Zefri Ariff, yang kerap menampilkan rumah dan ruang domestik sebagai representasi kebangsaan, H.MAR justru mengolah rumah sebagai simbol dialektika antara kesunyian individu dan keterbatasan komunal. Inilah yang membedakan posisi H. MAR dalam khazanah puisi Brunei modern: ia menghadirkan rumah bukan sekadar tempat fisik, melainkan metafora identitas diri sekaligus bangsa yang sedang mencari makna “warna” dalam kehidupan modern.
Sebagaimana ditegaskan A. Teeuw, simbol dalam puisi adalah “kiasan yang melampaui dirinya sendiri, membuka lapisan makna baru yang terkait dengan pengalaman kolektif maupun individual” (Sastra dan Ilmu Sastra, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984). Maka, rumah dalam puisi H.MAR adalah kiasan yang bekerja pada dua level: pengalaman personal penyair, dan realitas sosial Brunei.
Dengan demikian, posisi H.MAR dapat dibaca sebagai penyair yang menghubungkan ruang privat dengan ruang kolektif, membangun puisi yang reflektif-argumentatif tentang eksistensi individu dan kebersamaan masyarakat Brunei. Ia menempati posisi unik dalam sastra Brunei, karena berhasil menyeimbangkan suara batin penyair dengan representasi simbolis bangsa.
E. H. MAR dalam Dialog Puitik dengan Penyair Indonesia
H. MAR tidak berdiri sendiri dalam lanskap sastra serumpun. Untuk memahami posisi kepenyairannya, kita perlu menempatkannya dalam percakapan dengan penyair-penyair Indonesia. Hal ini penting karena puisinya, dengan simbol keseharian, spiritualitas, dan kesadaran sosial, memiliki kedekatan dengan tradisi puitik Indonesia.
Sebelum H.MAR, dunia sastra Brunei telah diperkenalkan oleh sejumlah nama seperti Mas Nordin, Jahid Haji Mohamad, dan Shukri Zain. Generasi sesudahnya muncul Muslim Burmat dan Siti Norkhalbi Haji Wahsalfelah. Namun, dalam konteks internasional, Brunei belum melahirkan penyair dengan resonansi sekuat Indonesia atau Malaysia. Di tengah situasi itu, H.MAR tampil sebagai figur yang paling menonjol.
Perbandingan pertama dapat ditarik dengan D. Zawawi Imron, seorang penyair Madura yang memadukan spiritualitas dengan simbol-simbol budaya lokal. Dalam sajaknya ia menulis:
CELURIT EMAS
roh-roh bebunga yang layu sebelum semerbak itu mengadu ke hadapan celurit yang ditempa dari jiwa.
celurit itu hanya mampu berdiam, tapi ketika tercium bau tangan yang pura-pura mati dalam terang dan bergila dalam gelap
ia jadi mengerti : wangi yang menunggunya di seberang. meski ia menyesal namun gelombang masih ditolak singgah ke dalam dirinya.
nisan-nisan tak bernama bersenyuman karena celurit itu akan menjadi taring langit, dan matahari akan mengasahnya pada halaman-halaman kitab suci.
celurit itu punya siapa? amin !”
1983
(Celurit Emas, Surabaya: Bintang Surabaya, 1986:27).
Celurit, senjata khas Madura, di tangan Zawawi diangkat menjadi simbol spiritual dan kultural. Ia tidak lagi sekadar benda tajam, melainkan lambang eksistensi manusia di hadapan Tuhan.
Hal yang serupa kita temukan dalam puisi H.MAR “Rumah Kita” (1998), ketika rumah kecil di atas bukit, karena cahaya bulan, tampak seperti istana kaca: “//…// Ketika bulan mengambang penuh, rumah kecil itu hampir menyerupai sebuah istana kaca./ Dan lampunya berwarna kuning dan merah.//…” Di sini, rumah sederhana menjelma simbol kemuliaan. Seperti celurit bagi Zawawi, rumah bagi H.MAR adalah lambang budaya sekaligus spiritualitas.
Perbandingan kedua bisa ditarik dengan Abdul Hadi W.M., penyair sufistik Indonesia. Dalam puisinya, Abdul Hadi menulis:
TERGANTUNG PADA ANGIN
Pada awan kita bertahan, dari bumi yang mau menarik
kita kembali dan matahari yang ingin mematahkan
ketenangan uap mengepul dan bermimpi, seperti terang
pada lampu buat bayang-bayang yang mudah hilang.
Kemana lagi kita akan menghindar dan mengambang?
Tergantung pada angin yang bertiup kencang atau pelahan.
1975
(Tuhan Kita Begitu Dekat, Jakarta: Komodo Books, 2012:43).
Bagi Abdul Hadi, angin adalah medium kosmik: pembawa doa, rahasia, sekaligus tanda transendensi. Pandangan spiritual ini berdekatan dengan pengucapan H.MAR dalam sajak Rumahku (1998): “Hujan telah turun. Dan bumi/ pun basah. Tidak pula aku dengar suara orang bernyanyi.// …// Hujan telah turun. Dan mengapa aku/ masih di dalam rumah!”
“Hujan” dalam sajak ini bukan sekadar gejala alam, melainkan simbol rahmat dan kehidupan. Namun, sang penyair tetap “di dalam rumah”, sebuah metafora keterasingan eksistensial. Tarik-menarik antara rahmat (kosmik) dan kesunyian (eksistensial) ini memiliki resonansi dengan gaya sufistik Abdul Hadi.
Dari kedua perbandingan tersebut, dapat ditarik refleksi bahwa kepenyairan H.MAR mengandung DNA puitik Nusantara:
1. Simbol keseharian yang ditransendensikan (rumah, hujan) sebagaimana Zawawi Imron mengangkat celurit;
2. Kerinduan spiritual yang serupa dengan pencarian sufistik Abdul Hadi W.M. ;
3. Akar budaya Melayu-Nusantara yang kuat, sehingga puisinya terasa akrab bagi pembaca Indonesia.
Dengan demikian, H.MAR tidak hanya representasi Brunei, melainkan juga bagian dari jagat puitik Nusantara. Ia hadir sebagai jembatan sastra serumpun, memperlihatkan bahwa batas negara tidak mampu membatasi arus besar kebudayaan Melayu-Indonesia.
Jika Chairil Anwar menandai lahirnya puisi modern Indonesia, D. Zawawi Imron memperlihatkan kekuatan lokalitas spiritual, dan Abdul Hadi W.M. menyingkap kosmologi sufistik, maka H.MAR menghadirkan Brunei ke dalam ruang percakapan Nusantara melalui simbol rumah dan hujan. Pada titik itu, ia bukan hanya penyair Brunei, tetapi juga penyair Nusantara.
F. H.MAR sebagai Jembatan Sastra Serumpun
1. Konsep Ruang Puitik Nusantara
Ruang Puitik Nusantara dapat dipahami sebagai medan estetik dan spiritual yang melampaui batas politik modern, di mana bahasa, simbol, dan imajinasi para penyair serumpun (Indonesia, Malaysia, Brunei, Patani, dan Singapura) saling bertaut dalam satu kosmos kebudayaan. Ruang ini tidak lahir dari kesepakatan formal, melainkan dari sejarah panjang pertemuan bahasa Melayu dan kebudayaan Islam di kawasan Asia Tenggara.
Ruang tersebut bersifat terbuka dan transnasional, namun pada saat yang sama berakar pada lokalitas. Setiap wilayah membawa kekhasannya: Indonesia dengan pluralitas etnik dan budaya, Malaysia dengan kesadaran nasionalisme Melayu, Brunei dengan tradisi kerajaan dan keagamaan, serta Patani dengan perlawanan identitas minoritas Muslim di Thailand. Dari perbedaan inilah lahir keberagaman citra puitik yang sekaligus memperkaya kesatuan ruang puitik Nusantara.
Sebagaimana dikemukakan oleh Sutan Takdir Alisjahbana, bahasa Melayu telah menjadi pengikat kebudayaan Nusantara sejak berabad-abad, karena kelenturan dan keterbukaannya menyerap nilai baru tanpa kehilangan jati dirinya (Jurnal Pujangga, Vol. 7, No.2, Desember 2021). Maka, bahasa adalah fondasi utama terbentuknya ruang puitik ini, sementara imajinasi dan pengalaman spiritual adalah jiwanya.
Azhar Ibrahim menegaskan bahwa tradisi intelektual dan kultural Melayu-Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai warisan, tetapi juga sebagai wacana hidup yang terus-menerus ditafsirkan ulang oleh generasi penyair, cendekia, dan pemikirnya (Ibid.). Pandangan ini menekankan bahwa Ruang Puitik Nusantara bukan sekadar geografi imajinatif, tetapi medan dialog intelektual dan spiritual yang hidup dari kontinuitas dan interpretasi ulang para penyair serumpun.
2. H.MAR dan Posisi Brunei dalam Ruang Puitik Nusantara
Dalam konteks itu, H.MAR hadir sebagai figur penting dari Brunei. Meskipun negara asalnya kecil secara geografis, kontribusinya tidak marginal. Justru dari “ruang kecil” itu ia mengangkat simbol-simbol puitik yang akrab bagi pembaca serumpun: hujan, rumah, taman, dan cahaya bulan. Semua itu bukan sekadar citra lokal, melainkan lambang universal yang diterima dalam horison Nusantara.
H. MAR membuktikan bahwa karya dari Brunei mampu menembus ruang puitik yang sama dengan penyair Indonesia dan Malaysia. Dalam puisinya, kita merasakan perjumpaan antara simplicity (kesederhanaan lambang) dan transcendence (kedalaman spiritual).
a. Akar Kultural yang Sama
Bahasa Melayu Brunei yang ia gunakan hanya sedikit berbeda dari bahasa Indonesia. Hal ini menjadikan puisinya segera bisa dipahami lintas negara. Kesamaan linguistik ini mengingatkan kita bahwa akar Melayu-Indonesia masih sangat kuat.
Abdul Hadi W.M. menegaskan hal tersebut: Puisi Nusantara, baik di Indonesia, Malaysia, maupun Brunei, sesungguhnya bersumber pada akar sufistik yang sama: mencari kebenaran, cinta, dan ketuhanan (Hermeneutika, Estetika, dan Religiusitas, Yogyakarta: Matahari, 2004).
Kutipan ini memperlihatkan bahwa meski berbeda negara, para penyair tetap berakar pada visi spiritual bersama yang tumbuh dari khazanah Melayu-Islam.
b. Kesamaan Simbolik
Dalam “Rumahku’ dan ‘Rumah Kita’, H.MAR menjadikan rumah sebagai simbol relasi individu dengan komunitas. Rumah kecil di atas bukit berubah menjadi istana kaca ketika disinari bulan. Simbol ini menunjukkan transendensi: dari keseharian menuju kemuliaan.
Tradisi simbolik semacam ini juga terlihat pada D. Zawawi Imron dengan citra celurit Madura, atau Abdul Hadi W.M. dengan laut dan angin. Kesamaan pola simbolik ini membuktikan bahwa penyair serumpun bergerak dalam kosmos imajinasi yang sama meski berangkat dari lokalitas masing-masing.
c. Kesadaran Spiritual dan Sosial
H. MAR memadukan kesadaran spiritual dengan refleksi sosial. “Hujan” bukan hanya fenomena alam, melainkan lambang rahmat Ilahi. Sementara “diam di dalam rumah” menyiratkan keterasingan manusia di tengah modernitas. Tradisi semacam ini juga berakar dalam sufisme Nusantara, dari Hamzah Fansuri hingga Amir Hamzah.
Kehadiran spiritualitas dalam puisinya memperlihatkan bahwa ruang puitik Nusantara tidak bisa dipisahkan dari pengalaman religius masyarakatnya.
d. Peran sebagai Representasi Brunei
Dalam peta sastra Brunei, sejumlah nama lain seperti Mas Nordin, Jahid Haji Mohamad, dan Shukri Zain pernah berperan. Namun, pada era kontemporer, H.MAR tampil sebagai representasi paling kuat di mata internasional. Partisipasinya dalam forum Mastera dan dialog dengan sastrawan Indonesia-Malaysia menjadikannya wajah Brunei yang paling dikenal.
Dengan demikian, ia berfungsi sebagai diplomat kultural, yang menghubungkan Brunei dengan dunia sastra serumpun.
e. Kontribusi terhadap Sastra Nusantara
Jika Chairil Anwar menjadi ikon lahirnya puisi modern Indonesia, Usman Awang di Malaysia menghadirkan kesadaran sosial kemanusiaan, dan Abdul Hadi W.M. merumuskan kosmologi sufistik Nusantara, maka H.MAR berperan menghadirkan Brunei ke dalam dialog ini. Ia bukan hanya mewakili bangsanya, tetapi juga mengikat kembali benang merah sastra Nusantara yang sempat tercerai-berai oleh batas politik negara.
H. MAR membuktikan bahwa sastra serumpun tidak mengenal sekat politik. Puisinya menegaskan adanya Ruang Puitik Nusantara: sebuah medan imajinasi dan spiritualitas yang berakar pada bahasa Melayu dan sufisme, tetapi terbuka pada kearifan lokal setiap wilayah. Dalam ruang ini, simbol-simbol keseharian ditransendensikan menjadi lambang universal.
Dengan demikian, H.MAR adalah jembatan yang menyatukan Brunei dengan Patani, Singapura, Malaysia, dan geobudaya Indonesia Raya dalam satu denyut budaya Melayu-Nusantara.
G. Meneguhkan Sastra Melayu-Nusantara di Tengah Arus Global
Dari uraian sepanjang esai ini dapat ditarik simpulan bahwa H.MAR merupakan penyair Brunei paling menonjol pada era kontemporer. Kehadirannya tidak hanya merepresentasikan suara sastra Brunei, melainkan juga menggemakan denyut kultural yang akrab bagi pembaca Indonesia dan Malaysia.
Puisinya melampaui batas negara, masuk ke dalam ruang puitik Nusantara, ruang imajinasi bersama yang dibentuk oleh akar bahasa Melayu, kosmologi sufistik, serta kearifan lokal yang beragam namun serumpun. Simbol-simbol keseharian seperti hujan, rumah, cahaya bulan, dan taman larangan yang muncul dalam puisinya bukan sekadar representasi lokal Brunei, melainkan juga lambang universal yang dapat dikenali, dirasakan, dan dimaknai oleh masyarakat di seluruh kawasan Nusantara.
Dengan demikian, H.MAR dapat dibaca sebagai “penyair Indonesia yang lahir di Brunei”, dalam makna kultural dan puitik, bukan administratif. Ia membuktikan bahwa sastra Nusantara tetap menyatu sebagai jalinan imajinasi serumpun, meskipun garis politik negara memisahkan. Pada titik inilah, H.MAR hadir sebagai jembatan penting yang meneguhkan eksistensi sastra Melayu-Nusantara di tengah arus global. ***
Abdul Wachid B.S. (Guru Besar UIN Saizu, Purwokerto)