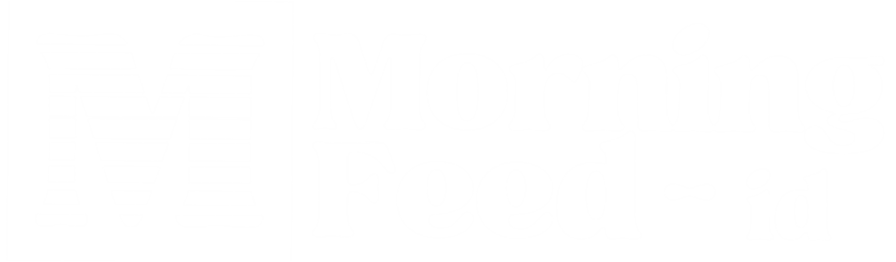Radea Juli A Hambali, Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung
80 tahun kemerdekaan adalah capaian yang patut disyukuri. Bangsa ini telah melewati pergolakan sejarah, mengusir penjajah, membangun republik, dan menapaki jalan panjang pembangunan. Namun, di tengah segala kemajuan itu, ada pertanyaan mendasar yang patut diajukan: apakah kemerdekaan yang telah lama kita raih ini telah mematangkan laku spiritual dan sosial? Apakah kita sudah benar-benar merdeka dari belenggu prasangka, kebencian, dan intoleransi terhadap yang beda dan tak sama?
Pertanyaan ini tidak mengada-ngada, sebab jawabannya tercermin dalam kenyataan sehari-hari. Belum lama ini, kita dikejutkan oleh peristiwa pembubaran ibadah umat Kristiani di Sukabumi dan penolakan perayaan di Padang yang menampar kesadaran kita. Harus kita akui, dua peristiwa ini bukan insiden tunggal yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola yang berulang. Ia seolah menjadi bukti bahwa di balik retorika kebhinekaan, kita masih rentan terperosok ke dalam kubangan intoleransi.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati hak-hak orang lain,” begitu kata Bung Karno suatu waktu mengingatkan. Peringatan ini mengandung pesan sederhana namun mendalam: kemerdekaan sejati tidak hanya diukur dari kemampuan membangun ekonomi atau kekuatan militer, melainkan dari kemauan dan kemampuan melindungi hak-hak semua warga tanpa kecuali. Dalam konteks kehidupan beragama, itu berarti memastikan bahwa setiap orang bebas beribadah sesuai keyakinannya, tanpa intimidasi dan tanpa rasa takut.
Namun kenyataannya, kedewasaan spiritual dan sosial kita masih belum kokoh. Kedewasaan spiritual bukan hanya kesalehan ritual, melainkan kemampuan menjadikan agama sebagai mata air kasih, bukan alat untuk membatasi. Sementara kedewasaan sosial adalah keberanian untuk menjamin keadilan dan kesetaraan di ruang publik, meskipun itu berarti membela hak mereka yang berbeda keyakinan.
Fenomena intoleransi yang berulang menunjukkan bahwa kita masih mengidap defisit pada dua kedewasaan ini. Agama kerap direduksi menjadi bendera kelompok, dan ruang sosial sering kali dipenuhi curiga dan syak wasangka.
Kurikulum Cinta
Saya kira, di sinilah relevansi Kurikulum Cinta yang digagas Menteri Agama, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA menemukan momentumnya. Kurikulum Cinta harus ditegaskan sebagai bukan sekadar konsep pendidikan formal, tetapi juga sebagai strategi kebudayaan untuk membentuk manusia yang utuh (berpikir kritis, berjiwa empati, dan berani merayakan perbedaan). Ia tidak sekadar menekankan anak didik untuk hafal sila Pancasila atau pasal-pasal UUD, tetapi menanamkan nilai-nilai itu dalam perilaku dan tindakan yang kongkrit di tengah-tengah masyarakat yang beragam.
Melalui Kurikulum Cinta, siswa belajar bahwa menjaga ibadah orang lain sama sucinya dengan menjaga ibadahnya sendiri. Mereka harus dibiasakan berdialog lintas iman, bukan untuk meleburkan keyakinan, tetapi untuk memahami dan menghormati. Mereka diajak memandang keberagaman sebagai ladang untuk memperluas cakrawala pemahaman, bukan sebagai medan pertempuran ideologis.
Kurikulum Cinta harus menjadi strategi untuk menggabungkan pelatihan kognitif, afektif, dan moral. Ia harus menjadi magnet yang mengajak peserta didik mempraktikkan empati melalui proyek sosial, diskusi lintas budaya, dan kerja sama lintas agama. Pendidikan semacam ini bukan tambahan pelajaran, tetapi inti dari pendidikan kebangsaan yang sesungguhnya.
Dari Kebanggaan ke Kedewasaan
Menjelang delapan dekade kemerdekaan, kita dihadapkan pada pilihan: puas dengan kebanggaan simbolis atau bergerak menuju kedewasaan substansial. Kebanggaan simbolis adalah sekadar mengulang narasi keberagaman dalam upacara dan slogan, sementara kedewasaan substansial adalah menjadikannya kenyataan hidup yang dirasakan semua warga negara, dari kota besar hingga pelosok desa. Dari Sabang sampai Merauke.
Kita harus mengakui bahwa kemerdekaan kita belum tuntas jika masih ada warga yang dihalangi untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Kita belum benar-benar merdeka jika perbedaan iman masih dipersepsi sebagai ancaman. Kemerdekaan yang utuh adalah kemerdekaan yang membebaskan dari rasa takut terhadap perbedaan, membebaskan dari prasangka yang diwariskan, dan membebaskan dari kebiasaan membatasi ruang hidup orang lain demi kenyamanan diri sendiri.
Maka bagi saya, penghalang bagi kemerdekaan yang utuh dan tuntas itu adalah intoleransi, fanatisme sempit, dan arogansi mayoritas. Dan kita harus berani dan sanggup menyingkirkannya jauh-jauh dari kehidupan sosial kita.
Kemerdekaan yang Berjiwa Cinta
Peringatan 80 tahun kemerdekaan seharusnya tidak hanya menjadi perayaan nostalgia, tetapi juga momentum evaluasi nasional. Apakah kita telah menjadi bangsa yang matang dalam mengelola keberagaman? Apakah kita sudah mewariskan pada generasi mendatang sebuah negeri yang bukan hanya damai di permukaan, tetapi juga tenteram di hati?
Kurikulum Cinta adalah undangan untuk membangun kemerdekaan yang punya jiwa. Ia mengajak kita menjadikan cinta sebagai kompas moral, agar semboyan Bhinneka Tunggal Ika berhenti menjadi sekadar slogan yang diteriakan di mimbar pelatihan dan penataran tetapi benar-benar berdenyut di nadi kehidupan sosial kita.
Karena pada akhirnya, Indonesia yang berumur 80 tahun tidak akan diingat hanya karena gedung-gedungnya yang menjulang atau teknologinya yang maju, tetapi karena kemampuannya menjaga taman keberagaman ini tetap hidup dan indah, di mana setiap bunga, apa pun warnanya, bisa tumbuh tanpa takut dipetik sebelum mekar. _Allahu a’lam bishawab_
Radea Juli A Hambali, Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung