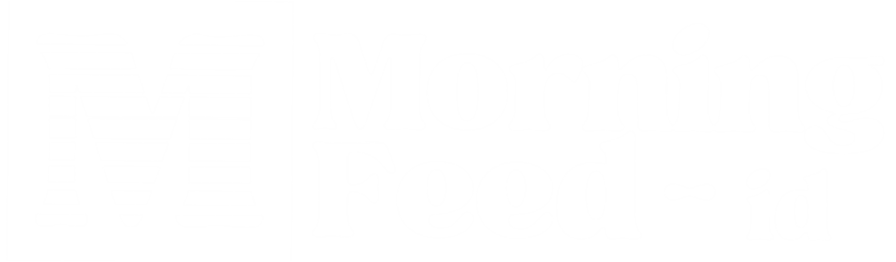Pada setiap tanggal 22 April, terdapat momen reflektif global dalam kerangka memikirkan bumi. Momen tersebut adalah Hari Bumi. Bumi membutuhkan perlakuan tersendiri dalam merawat dan melestarikan karena kondisi yang diterimanya sebagai akibat ulah manusia. Hari Bumi hadir untuk kembali membangunkan kesadaran bersama akan makna penting bumi bagi kehidupan. Saat berbagai langkah terkait pelestarian bumi terasa artifisial dan berbagai keresahan lingkungan tidak diungkap, maka diperlukan tindakan etis dengan melakukan langkah reflektif dan restrospektif.
Bumi sejatinya sudah menua, merujuk pada kapasitas bumi yang tidak lagi optimal dalam mendukung kehidupan. Hal ini bisa ditemukan pada berbagai perubahan dan degradasi lingkungan sebagai akibat aktivitas alami maupun manusia. Beberapa puluh tahun yang lalu, tidak ditemui berbagai masalah yang kini menghantui bumi, seperti degradasi lahan dan sumber daya alam, perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, dan persoalan yang dihadapi bumi lainnya. Beberapa lembaga internasional memberikan laporan mengenai bermacam gejala yang disebut yang pada akhirnya menegaskan beban bumi yang kian mencemaskan.
Organisasi pangan dan pertanian dunia (Food and Agriculture Organization –FAO) melaporkan berbagai kecenderungan yang memengaruhi fungsi kelestarian bumi. FAO menyoroti degradasi lahan sebagai ancaman global terhadap ketahanan pangan, keanekaragaman hayati, dan stabilitas ekosistem. Sekitar 33 persen lahan global telah terdegradasi dan memengaruhi 1,5 miliar orang yang bergantung langsung pada lahan untuk penghidupan mereka. Laporan tersebut dituangkan dalam dokumen State of the World’s Land and Water Resources for Food and Agriculture (SOLAW, terbit tahun 2022) dan State of the World’s Forests (SOFO, terbit 2023).
Persoalan lain yang dihadapi bumi adalah perubahan iklim. Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), perubahan iklim adalah perubahan signifikan dalam sistem iklim bumi yang berlangsung selama dekade hingga ribuan tahun, yang dapat diukur melalui indikator seperti suhu permukaan bumi, permukaan laut, dan komposisi atmosfer. Problem emisi gas rumah kaca, deforestasi, pertanian dan peternakan yang memperkuat gas rumah kaca, serta limbah dan polusi adalah berbagai penyebab perubahan iklim. IPCC dan COP selalu mengingatkan isu perubahan iklim setiap tahunnya. Conference of parties (COP), meski dinilai minim menawarkan kemajuan dalam penanggulangan bencana perubahan iklim, merupakan ajang terkemuka berbagai negara untuk membahas problem perubahan iklim.
Kehilangan biodiversitas (spesies, ekosistem, dan keragaman genetik) merupakan problem lain yang dihadapi bumi saat ini. Data dari Intergovernmental Science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) tahun 2024 menegaskan bahwa sekitar 1 juta spesies tumbuhan dan hewan (dari sekitar 8 juta spesies yang diketahui) terancam punah dalam beberapa dekade mendatang, kecuali tindakan signifikan diambil. IPBES menggarisbawahi bahwa skor tersebut menunjukkan tingkat kepunahan 10 hingga 100 kali lebih cepat daripada rata-rata selama 10 juta tahun terakhir. Laporan ini menggarisbawahi bahwa planet bumi jelas tengah menghadapi bahaya biodiversitas yang mengundang kemasygulan.
Indonesia, sebagai salah satu negara megadiversitas dengan 17 persen biodiversitas dunia, menjadi fokus penting dalam laporan IPBES karena kekayaan hayati sekaligus ancaman besar yang dihadapinya. Indonesia adalah rumah bagi spesies ikonik seperti orang utan, harimau sumatera, badak Jawa, dan komodo yang hampir semuanya terancam punah. Di tengah persoalan tersebut, Indonesia memiliki perbedaan data deforestasi yang cukup mencolok. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Global Forest Watch (GFW), dan Auriga Nusantara memiliki perbedaan signifikan. Tahun 2023, Auriga Nusantara mencatat adanya deforestasi pada 257.384 hektar (naik dari 230.760 hektar pada 2022), Global Forest Watch mencatat 1,4 juta tutupan lahan yang hilang, namun KLHK justru mencatat adanya penurunan deforestasi sebesar 104 ribu hektar.
Konsep Ekoteologi
Perbedaan ini menjelaskan adanya penafsiran yang berbeda terhadap sebuah fenomena dengan bumi sebagai pertaruhannya. Kebijakan yang ditempuh untuk merawat bumi terang didasarkan pada data yang tersedia. Tentu saja menjadi pertanyaan besar saat ditemukan adanya perbedaan data yang mencolok oleh sesama lembaga yang dikenal luas oleh publik. Oleh karenanya, diperlukan sebuah perspektif etis dalam memandang bumi beserta beragam tanda yang dibuatnya dalam sengkarut perbedaan data tersebut. Hal ini menjadi keniscayaan karena masyarakat Indonesia dikenal dengan tingkat religiositas yang signifikan (98 persen masyarakat Indonesia dikenal religius, BPS tahun 2020).
Dalam batas ini dikenal adanya pandangan ekoteologi. Pandangan yang berasal dari Menteri Agama Nasaruddin Umar ini menawarkan pendekatan dan nuansa yang relatif baru dalam memandang bumi. Ekoteologi adalah pendekatan teologi yang mengintegrasikan spiritualitas, iman, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Konsep ini memandang alam sebagai ciptaan suci yang harus dijaga dan karenanya sikap jujur diperlukan dalam merawatnya. Ekoteologi menekankan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan, dengan prinsip bahwa menjaga lingkungan adalah panggilan spiritual. Dalam berbagai ajaran agama di Indonesia, ekotelogi lekat dalam berbagai pemahaman dasarnya.
Dalam pandangan Islam, konsep khalifah (pengelola bumi) dan mizan (keseimbangan alam) dalam Al-Qur’an (QS. Ar-Rahman: 7–9) mendorong pelestarian lingkungan, sementara Kristen memandang penting ajaran penatalayanan (stewardship) berdasarkan Kejadian 1:26–28, yang menyerukan manusia untuk merawat ciptaan. Pandangan ini senapas dengan ajaran agama Hindu dalam prinsip Tri Hita Karana (harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan) yang diterapkan dalam praktik seperti sistem subak. Sejalan dengan ajaran agama besar lainnya, Buddha memiliki konsep interdependensi dan kasih sayang terhadap semua makhluk hidup yang dapat menjadi landasan ekotelogi. Sementara itu, ekoteologi juga menjadi pandangan mendasar kepercayaan adat, semisal suku Dayak yang memandang hutan sebagai entitas suci, mencerminkan lokalitas ekoteologi.
Pada dasarnya ekoteologi memiliki relevansi kuat dengan Hari Bumi. Ekoteologi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia, yang sudah memiliki nilai moral tinggi tetapi kurang bertindak, dengan menjadikan Hari Bumi sebagai momen ibadah kolektif untuk menjaga ciptaan. Lebih dari itu, Hari Bumi dapat memanfaatkan institusi keagamaan (masjid, gereja, pura, dan vihara) dan tokoh agama sebagai kanal edukasi, dan meningkatkan pemahaman tentang perubahan iklim, deforestasi, serta degradasi lahan.
Tema Hari Bumi 2025, “Our Power, Our Planet“, salah satunya menyerukan transisi global ke energi terbarukan untuk mengatasi krisis iklim. Kesepakatan global terkait hal ini menargetkan kapasitas energi bersih mencapai tiga kali lipat pada 2030. Dalam konteks ini, ekoteologi relevan kfgarena memberikan landasan spiritual untuk memperkuat kesadaran moral, mengatasi skeptisisme, dan mendorong aksi nyata di Indonesia, seperti melalui masjid ramah lingkungan, gereja hijau, atau praktik adat. Dengan memanfaatkan nilai-nilai Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan adat, ekoteologi dapat menjadikan Hari Bumi 2025 sebagai momen transformasi spiritual dan lingkungan, mendukung pelestarian biodiversitas dan ketahanan iklim di Indonesia.
Saiful Maarif, Bekerja pada Ditjen Pendidikan Islam Kemenag