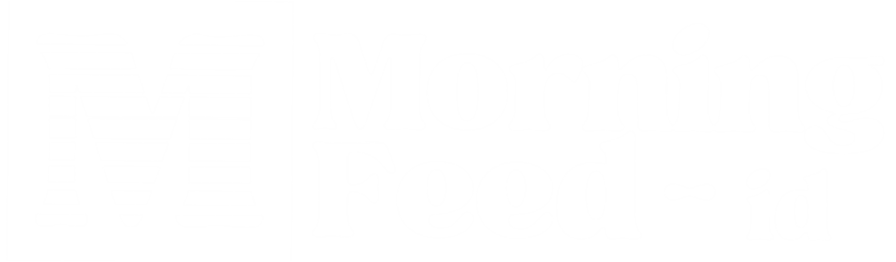Kita hidup di tengah dunia yang kian panas, bising, dan rapuh. Krisis lingkungan bukan lagi sebagai ramalan masa depan, melainkan realitas hari ini. Perubahan iklim ekstrem, polusi udara dan air, deforestasi, banjir bandang, kekeringan berkepanjangan, dan hilangnya keanekaragaman hayati hanyalah sekelumit potret buram bumi kita.
Indonesia, dengan segala kekayaan ekologinya, tak luput dari ancaman degradasi lingkungan yang mengancam kehidupan, kini dan nanti.
Namun krisis ekologis bukan semata urusan teknis atau kebijakan. Ia adalah krisis nilai, spiritual, dan peradaban. Kita telah terlalu lama memandang bumi dengan lensa eksploitatif, memisahkan akal dari iman, dan menjauhkan kebijakan dari etika.
Dalam situasi ini, kita patut bertanya, di mana posisi agama dan negara dalam upaya menyelamatkan bumi yang kita huni bersama?
Etika ekologis
Agama-agama besar dunia sejatinya telah lama meletakkan dasar etika lingkungan. Dalam Islam, manusia diberi mandat sebagai “khalifah fi al-ardh” atau wakil Tuhan di bumi, yang berarti bertanggung jawab menjaga dan merawat ciptaan, bukan malah merusaknya.
Larangan menciptakan kerusakan di bumi (fasad fi al-ardh) dalam al-Qur’an sejatinya bukan sekadar larangan kriminalitas sosial tapi mencakup perusakan ekosistem dan ketidakseimbangan alam.
Islam juga mengajarkan prinsip “mizan” atau keseimbangan, yang menegaskan bahwa alam semesta diciptakan dalam takaran yang presisi dan seimbang.
Kristen mengenalkan konsep “stewardship of creation”, yaitu manusia sebagai pengelola alam, bukan pemilik mutlak.
Demikian pula Hindu dan Budha mengajarkan “ahimsa” atau anti-kekerasan, termasuk terhadap makhluk hidup dan juga alam semesta.
Semua agama, dengan demikian, pada hakikatnya mengajarkan harmoni antara manusia dan alam. Di dalamnya tertanam etika ekologis transendental, yakni kesadaran bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Tuhan.
Dalam kerangka ini, gagasan “ecological civilization” dari filsuf China kontemporer, Tu Weiming (2001), menjadi relevan. Ia menegaskan pentingnya spiritualitas dalam menghadapi krisis ekologi modern. Bagi Tu, keberlanjutan lingkungan hanya mungkin dicapai jika manusia kembali kepada akar nilai-nilai moral yang tertanam dalam tradisi budaya dan agama.
Di sisi lain, sebagian besar kebijakan lingkungan hidup di Indonesia, juga di banyak negara lainnya, berbasis pendekatan teknokratis dan ekonomi-sentris. Pemerintah mendorong carbon trading, green energy, atau sustainable development yang lebih menekankan aspek pasar, teknologi, dan infrastruktur.
Namun, pendekatan semacam itu kerap tidak menyentuh akar permasalahan, yakni gaya hidup konsumtif, keserakahan, dan ketimpangan relasi antara manusia dengan alam.
Sosiolog lingkungan, John Barry, dalam Rethinking Green Politics (1999), mengingatkan bahwa kebijakan lingkungan yang hanya berfokus pada efisiensi teknologi tanpa menata ulang nilai-nilai kehidupan hanya akan menunda kehancuran ekologis.
Oleh karena itu, negara tak cukup hanya membuat undang-undang atau peraturan teknis. Dibutuhkan narasi nilai yang menumbuhkan etos baru, yakni dari manusia sebagai penguasa, menjadi manusia sebagai penjaga.
Kebijakan Kolaboratif
Gagasan mengenai integrasi antara doktrin agama dan kebijakan negara bukanlah agenda yang bersifat konservatif, tapi ini adalah langkah progresif untuk menyatukan etika dan struktur.
Di satu sisi, agama mampu membentuk kesadaran kolektif dan perubahan perilaku jangka panjang. Sedangkan pada sisi lain, negara memiliki instrumen regulasi, insentif, dan sanksi.
Beberapa inisiatif kolaboratif menunjukkan potensi besar dalam konteks sinergi ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Fatwa No. 04 Tahun 2014 tentang Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem. Fatwa ini menjadi dokumen penting yang menjembatani ajaran Islam dengan urgensi ekologis.
Begitu pula sejumlah tokoh lintas agama di Indonesia terlibat dalam deklarasi penyelamatan hutan adat di Kalimantan dan Papua. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun mulai menjajaki kerja sama dengan pesantren dalam program eco-pesantren.
Dari kacamata Daniel P. Scheid, dalam bukunya, The Cosmic Common Good (2016), peran agama dalam kebijakan publik perlu diperluas untuk membentuk “kemaslahatan kosmik”, sebuah pandangan bahwa kebaikan umum tidak hanya mencakup manusia, tetapi seluruh ciptaan.
Pandangan ini sejalan dengan doktrin maqashid al-syari‘ah yang menempatkan perlindungan alam sebagai bagian dari tujuan syariat Islam secara keseluruhan.
Namun tentu saja, integrasi ini menemui sejumlah tantangan. Sekularisme kebijakan masih menjadi tembok pemisah antara negara dan agama. Di sisi lain, politisasi agama serta defisit kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keagamaan juga menjadi kendala tersendiri.
Karenanya, diperlukan strategi sistematis untuk membangun kepercayaan dan sinergi. Pertama, literasi ekoteologi perlu diperkuat, agar umat memahami bahwa peduli lingkungan bukan sekadar tren tapi bagian dari iman.
Kedua, dialog lintas institusi, yakni antara negara, lembaga keagamaan, akademisi, dan masyarakat sipil perlu difasilitasi untuk menghasilkan rekomendasi dan tindakan bersama.
Ketiga, narasi-narasi religius harus masuk dalam dokumen kebijakan lingkungan, baik di tingkat nasional maupun lokal.
Sudah saatnya penyelamatan bumi tidak hanya menjadi domain teknokrat dan ilmuwan, tapi juga panggilan spiritual umat beragama. Dalam Islam, mencintai ciptaan Allah adalah bagian dari keimanan. Dalam pandangan K.H. Sahal Mahfudz, “mashlahat” atau kemaslahatan, tidak hanya mencakup manusia tapi juga seluruh alam semesta.
Kita membutuhkan kebangkitan ekospiritualitas publik, suatu gerakan kolektif yang memadukan kesalehan ekologis, etika transendental, dan keberpihakan kebijakan. Di titik inilah, integrasi agama dan negara bukan lagi menjadi pilihan tapi keniscayaan.
Seperti yang pernah dinyatakan Paus Fransiskus (2015) bahwa perubahan iklim bukan hanya soal teknologi tapi juga soal jiwa. Pernyataan ini menggugah kita bahwa penyelamatan bumi harus dimulai dari pergeseran kesadaran terdalam manusia.
Sebuah kesadaran bahwa bumi ini bukan milik kita semata, tapi titipan generasi mendatang yang harus kita jaga bersama.***
Ahmad Tholabi Kharlie (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
Tulisan ini sebelumnya terbit di kompas.com dengan judul yang sama. Simak link: https://nasional.kompas.com/read/2025/07/22/09000091/ekoteologi-dan-peran-negara