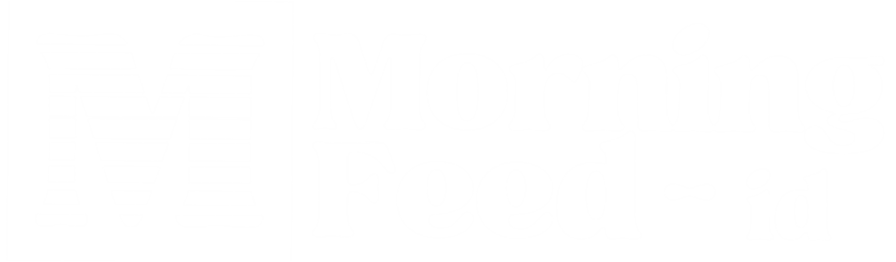Muhammad Fauzinudin Faiz (Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember & Khadim YASPPIBIS Jember)
Ketika Kementerian Agama memperkenalkan “Kurikulum Cinta” sebagai wajah baru pendidikan keagamaan, banyak yang bertanya: ke mana perginya “Moderasi Beragama”? Apakah ini sebuah perubahan arah, bahkan mungkin pembatalan terhadap kerangka moderasi yang selama ini menjadi narasi resmi pemerintah dalam menangkal ekstremisme dan menguatkan toleransi? Pertanyaan ini sah dan wajar. Namun, jawabannya tidak terletak pada dikotomi antara “moderasi” dan “cinta”, melainkan pada jalinan makna yang saling menguatkan antara keduanya. Alih-alih membaca ini sebagai pergeseran konseptual, kita seharusnya memahaminya sebagai pelebaran ruang batin dalam membumikan nilai-nilai keagamaan yang manusiawi, ramah, dan berpihak pada keberlangsungan hidup bersama.
Moderasi: Jalan Tengah dalam Keberagamaan
Sejak pertama kali diperkenalkan sebagai salah satu program strategis nasional, moderasi beragama telah menjadi kerangka epistemik yang kokoh dalam menghadapi polarisasi identitas keagamaan di Indonesia. Ia lahir bukan dari ruang kosong, melainkan dari kebutuhan historis untuk menjembatani antara semangat keislaman yang taat dan realitas sosial yang plural. Moderasi beragama menawarkan empat pilar utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal. Dalam praksisnya, moderasi tidak berarti netralitas apolitis, tetapi keberpihakan pada kemanusiaan yang adil dan beradab.
Namun, satu kritik mendasar terhadap proyek moderasi adalah sifatnya yang seringkali “teknokratis”, terlalu rasional, dan kadang kehilangan ruh afeksi yang seharusnya menjadi inti dari agama itu sendiri. Di sinilah pertanyaan-pertanyaan bermunculan: apakah moderasi cukup hanya dengan pelatihan dan modul? Apakah cukup menyentuh akar kesadaran masyarakat? Dalam banyak kasus, pendekatan moderasi memerlukan dialektika lebih dalam—yakni menghadirkan rasa, bukan hanya nalar.
Kurikulum Cinta: Bahasa Afeksi dalam Pendidikan Keagamaan
Kurikulum Cinta lahir bukan sebagai tandingan, melainkan sebagai pengisi kekosongan emosional dari kerangka moderasi. Ia menyentuh apa yang selama ini kadang terabaikan dalam narasi kebijakan: hati. Dengan menekankan empat pilar cinta—cinta kepada Tuhan (hablum minallah), cinta kepada sesama manusia (hablum minannas), cinta kepada alam (hablum bil bi’ah), dan cinta kepada bangsa (hubbul wathan)—kurikulum ini menarasikan ulang agama sebagai ruang kehadiran kasih, bukan sekadar kepatuhan normatif.
Konsep cinta ini tidak lahir dari romantisme kosong, tetapi dari akar spiritualitas Islam itu sendiri. Dalam khazanah tasawuf, cinta kepada Allah adalah puncak dari perjalanan keagamaan. Dalam fikih sosial, cinta menjadi dasar kepedulian terhadap sesama. Bahkan dalam teks-teks klasik, seperti al-Mawardi, al-Ghazali hingga al-Rumi, cinta menjadi etika mendasar dalam membangun relasi sosial dan negara. Maka, kurikulum cinta sebenarnya adalah pendalaman spiritual terhadap nilai-nilai moderasi, bukan pelariannya.
Selain itu, cinta bersifat inklusif. Ia tidak membedakan sebelum merangkul. Dalam konteks pendidikan, ini berarti mengajarkan siswa untuk tidak hanya “mengerti” nilai-nilai keberagamaan yang moderat, tetapi juga “merasakan” pentingnya kasih sayang, empati, dan kepedulian. Dengan demikian, kurikulum cinta menjadi ruang afektif yang melengkapi ruang kognitif moderasi.
Mengapa Penguatan, Bukan Pergantian
Menempatkan cinta sebagai fondasi baru dari pendidikan keagamaan bukan berarti mengganti moderasi, tetapi memperdalam dan memperluasnya. Moderasi memberikan kerangka berpikir, cinta memberikan daya gerak. Moderasi mengatur langkah, cinta menghidupkan hati yang melangkah. Jika moderasi adalah peta jalan, maka cinta adalah cahaya di sepanjang jalan itu.
Kekeliruan akan terjadi jika kita mempersepsikan keduanya dalam hubungan vis-à-vis, seolah keduanya saling meniadakan. Yang terjadi justru sebaliknya: kurikulum cinta menambal ruang yang belum disentuh moderasi. Ia tidak mengubah arah, tapi memperkaya narasi. Cinta menghadirkan dimensi afeksi yang sangat dibutuhkan dalam menginternalisasi nilai-nilai moderasi, terutama dalam konteks masyarakat pasca-konflik, sekolah-sekolah multikultural, dan ruang digital yang penuh ujaran kebencian.
Secara kebijakan, justru langkah ini bisa dibaca sebagai redefinisi strategis untuk memperkuat efektivitas moderasi itu sendiri. Kita belajar bahwa perubahan tagline bukan sekadar permainan kata, melainkan refleksi atas kebutuhan zaman. Moderasi, dengan segala kelebihannya, perlu dibumikan dalam bahasa yang lebih menyentuh, lebih menyatu dengan keseharian masyarakat. Dan cinta adalah bahasa itu.
Integrasi Nalar dan Rasa dalam Pendidikan Keagamaan
Agama, dalam intinya yang terdalam, selalu berangkat dari cinta—cinta kepada Sang Pencipta, cinta kepada ciptaan-Nya. Ketika negara melalui Kementerian Agama memperkenalkan “Kurikulum Cinta”, kita tidak sedang menyaksikan kematian moderasi, melainkan kelahirannya kembali dalam wajah yang lebih manusiawi. Inilah bentuk ijtihad kebijakan yang tidak menghapus gagasan lama, tetapi membacanya ulang dalam konteks baru. Dari moderasi ke cinta? Bukan pergantian. Ini adalah penguatan: dari nalar menuju rasa, dari regulasi menuju ruh.
Muhammad Fauzinudin Faiz (Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember & Khadim YASPPIBIS Jember)