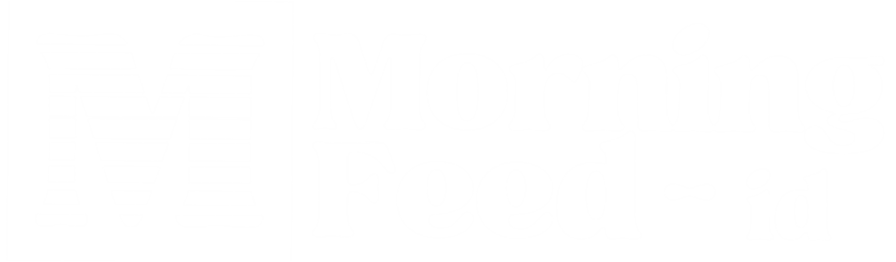Radea Juli A. Hambali (Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung)
Sebagaimana ramai diberitakan oleh berbagai media, Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar, M.A., menerima gelar Doctor of Divinity dari Hartford International University for Religion and Peace, Jumat (16/5/2025). Melampaui sekadar penghargaan akademik ataupun pengakuan formal dari dunia internasional, anugrah gelar Doctor of Divinity ini adalah cermin dari ketokohan Prof. Nasaruddin Umar, yang konsisten dalam membangun jembatan di tengah bentang perbedaan yang kerap menjadi jurang pemisah.
Di dunia yang mudah terpecah oleh eksklusivisme agama, etnosentrisme, dan polarisasi politik, hadirnya sosok seperti Prof. Nasaruddin Umar bisa dilihat sebagai lentera penjaga. Ia tak sekadar mengajarkan toleransi, tetapi juga merayakan keberagaman. Tak hanya berbicara perdamaian, tapi kesanggupan berjalan atas nama keberanian untuk mengupayakan rekonsiliasi, baik antaragama maupun antarmazhab dalam Islam.
Penjaga Kesadaran Kolektif
Saya kira, Prof. Nasaruddin bukanlah sosok yang berharap sorotan. Tapi Langkah-langkah yang dilakukannya dalam konteks merawat perdamaian antar iman telah membentuk gema tersendiri. Ia tidak hanya mengisi ruang-ruang akademik dengan tafsir dan pemikiran, tetapi juga berjalan menembus batas-batas sosial dan ideologis yang seringkali membeku dalam kecurigaan dan konflik. Dalam dirinya, kita mendapati kegigihan seorang ulama yang menolak kalah oleh sekat-sekat sempit tafsir tunggal dan eksklusivisme teologis.
Indonesia adalah negeri yang terus bergulat dengan keragamannya. Agama, etnisitas, dan sejarah menjadi simpul-simpul yang saling menarik, kadang menguatkan, kadang pula saling menegangkan. Dalam konteks inilah sosok seperti Prof. Nasaruddin menjadi oase, bukan hanya karena ucapannya tentang toleransi, tetapi karena laku hidupnya yang menjadi jembatan antara yang berbeda. Ia hadir bukan sebagai figur seremonial keagamaan, tetapi penjaga kesadaran kolektif bahwa keberagaman adalah rahmat, bukan ancaman.
Di banyak kesempatan, ia membuktikan bahwa dialog adalah cara yang paling bernilai dalam mengurai perbedaan. Dialog bukan tanda kelemahan iman, melainkan bentuk keberanian untuk memahami. Dalam pertemuan antaragama, ia tidak membawa panji superioritas, melainkan ketulusan untuk mendengar dan menjelaskan. Dalam forum-forum antarmazhab, ia tidak menciptakan ruang saling serang, tetapi ruang untuk saling menyapa.
Etika Kehidupan
Sebagai cendekiawan, beliau telah memberikan kontribusi besar dalam studi Islam, khususnya dalam bidang tafsir, tasawuf, dan gender. Namun lebih dari itu, yang membedakannya adalah kemampuannya mengubah ilmu menjadi etika kehidupan. Ia membaca wahyu bukan untuk mencari pembenaran, tetapi untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Barangkali, di sinilah letak kedalaman spiritualnya—agama tidak berhenti pada kata, tetapi menjadi jalan untuk mendekat kepada sesama.
Gelar Doctor of Divinity dari Hartford bukan hanya pengakuan akademik. Ia adalah pengakuan terhadap cara pandang yang mampu melihat agama sebagai kekuatan pemersatu. Lembaga ini dikenal sebagai pelopor dalam membangun dialog antaragama dan perdamaian lintas batas. Penghargaan ini juga menyentuh kesadaran kolektif kita sebagai bangsa, bahwa wajah Islam Indonesia yang damai, ramah, dan terbuka, perlu terus disuarakan. Sungguh, kita membutuhkan lebih banyak sosok yang mampu menampilkan agama sebagai pelita, bukan bara. Agama yang hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyembuhkan. Agama yang tidak terjebak dalam fanatisme simbolik, tetapi menjelma dalam kasih, keadilan, dan kepedulian sosial.
Membangun Dialog
Saya kira, Prof. Nasaruddin adalah contoh seorang cendekiawan muslim yang tidak perlu berteriak untuk didengar. Ia menyampaikan pesan melalui tindakan. Ia membangun dialog dengan menghadirkan diri, bukan hanya argumen. Ia merawat hubungan lintas iman dan lintas pandangan bukan untuk pencitraan, tetapi karena ia percaya bahwa perdamaian lahir dari keberanian untuk membuka diri pada yang lain.
Melalui dirinya, kita dapat belajar bahwa agama bukan doktrin di kepala atau ritual tubuh semata. Ia harus menjadi pengalaman yang hidup di hati dan diwujudkan dalam sikap. Dalam kehidupan sosial dimana identitas dan keyakinan kerap dibenturkan, Prof. Nasaruddin memilih jalan perjumpaan dengan sesama secara jujur berlandaskan cinta. Saya kira, Prof. Nazarudin meyakini bahwa iman yang otentik itu tidak menakutkan, apalagi menyingkirkan. Iman yang otentik adalah memeluk, merangkul, dan memulihkan.
Dalam konteks Indonesia yang kaya dengan perbedaan namun kerap rapuh dalam kohesi, barangkali dibutuhkan lebih banyak tokoh seperti Prof. Nasaruddin Umar yang bisa menunjukkan bahwa menjadi religius tidak harus berarti menjadi eksklusif. Bahwa menjadi beriman tidak berarti harus merasa paling benar. Melainkan, bahwa menjadi manusia beriman adalah yang berani hadir di tengah-tengah keragaman, dengan hati yang terbuka dan tangan yang terulur.
‘Ala kulii hal, gelar ini bukan hanya milik seorang menteri. Ia adalah warisan moral yang berharga bagi setiap anak bangsa. Ia juga adalah undangan untuk menyelami makna iman dalam ruang yang lebih luas dari sekadar ritus, yakni cinta kepada sesama, pada perjumpaan yang tulus, dan pada komitmen untuk terus mencari titik temu di tengah segala rupa perbedaan. Karena pada akhirnya, seperti yang pernah dikatakan Rumi, di luar ide tentang benar dan salah, ada sebuah ladang. Di sanalah aku akan menemuimu.” Allahu a’lam.
Radea Juli A. Hambali (Wakil Dekan III Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung)