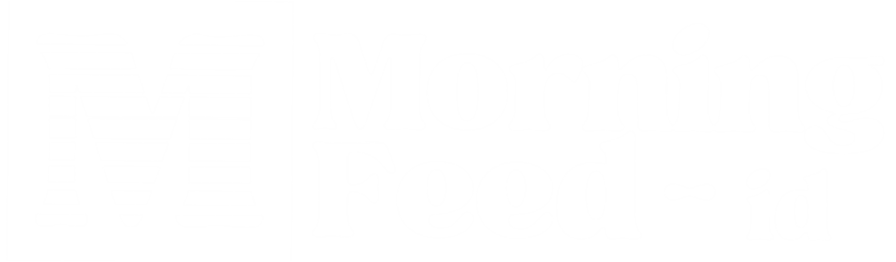Di tengah derasnya arus globalisasi yang mengguncang identitas, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) memikul tanggung jawab strategis: melahirkan generasi yang tidak hanya cakap secara akademis, tetapi juga matang secara spiritual dan teguh komitmen kebangsaannya.
Asesor-asesor yang dalam tugasnya melakukan visitasi akrediitasi ke UIN Jakarta, misal asesor akreditasi nasional dari LAMSAMA, LAMINFOKOM, atau ASIIN (akreditasi Internasional), kerap menyoroti visi keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan yang (secara resmi) diintegrasikan. Mereka ingin melihat bagaimana visi itu diimplementasikan dan bagaimana mengukur keberhasilannya. Tulisan ini, sedikit mengurai konsep kurikulum integrasi tersebut.
Kurikulum memang semestinya tidak sekadar menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai dan membentuk karakter. Kurikulum integrasi–begitu saya menyebutnya, menjadi ikhtiar untuk merespons tantangan zaman dengan mengintegrasikan aspek intelektual, spiritual, dan kebangsaan secara harmonis.
Dialog Nalar dan Wahyu
Integrasi keilmuan dan keislaman menjadi fondasi awal. Di ruang-ruang kuliah PTKIN, mahasiswa dengan konsentrasi bioteknologi misalnya, tidak hanya diajak membedah sel dan gen, tetapi juga mendalami etika reproduksi dari perspektif fikih kontemporer. Ketika membahas teori evolusi, diskusi diperluas dengan refleksi tentang penciptaan manusia dalam tafsir Al-Qur’an.
Di sinilah sains dan wahyu tidak berseberangan, tetapi berdialog di area harmoni yang luas. Mata kuliah seperti Islam dan Ilmu Pengetahuan atau Etika Profesi dalam Islam menjadi contoh nyata dari desain kurikulum integratif.
Dosen ditantang menyusun penugasan yang tidak hanya mengukur ketajaman analisis, tetapi juga kemampuan mahasiswa mengaitkan data empiris dengan prinsip tauhid dan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam atmosfer akademik semacam ini, mikroskop bertemu mushaf; laboratorium berdampingan dengan nilai-nilai transendental.
Cinta Tanah Air
Keislaman yang mendalam belum lengkap tanpa semangat keindonesiaan yang menyala. Di sinilah dimensi kebangsaan menjadi unsur penting dalam kurikulum integrasi PTKIN.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan penting diajarkan sebagai teori, juga harus diwujudkan dalam praktik nyata: kunjungan ke pesantren multietnis di Nusa Tenggara, pengabdian lintas agama di Papua, atau magang di desa tertinggal di pedalaman Kalimantan.
Bukankah masionalisme tidak dikostruksi melalui hafalan, tetapi melalui pengalaman langsung yang menumbuhkan empati, toleransi, dan cinta Tanah Air?
Oleh karena itu, kampus pun harus menjadi cerminan Indonesia dalam miniatur: ruang yang memberi tempat bagi keberagaman bisa tumbuh dan berinteraksi. Di dalamnya, jilbab berdialog dengan batik, budaya pesantren berpadu dengan riset ilmiah, dan organisasi mahasiswa menjadi medan perjumpaan antaridentitas.
Keindonesiaan dalam konteks ini merupakan pengalaman hidup yang dinamis–yang harus terus dilatih dan diuji. Sehingga bhineka tunggal ika benar-benar menjadi awareness. Perbedaan adalah kekayaan, sekaligus kekuatan bangsa.
Kurikulum Tiga Dimensi
Bahwa keilmuan, keislaman dan keindonesiaan bukanlah daftar mata kuliah, tetapi napas yang menghidupkan seluruh struktur kurikulum. Bgaimana agar sekali bernapas, tiga dimensi terlampaui.
Oleh karena itu, keberhasilan integrasi akan tampak dari cara bagaimana lulusan merespons realitas. Mampukah mereka mengembangkan teknologi tanpa kehilangan orientasi etis; menulis karya ilmiah yang menggabungkan riset lapangan dengan hikmah Qur’ani; serta tampil sebagai agen perubahan yang memperkuat kohesi sosial dan merawat kebhinekaan.
PTKIN memiliki potensi besar untuk menggerakkan visi ini. Modal sosial seperti jejaring pesantren, kredibilitas keilmuan keislaman, dan kedekatan dengan masyarakat merupakan kekuatan khas. Oleh karena itu, ruang akselerasi implementasi lkurikulum integrasi sangatlah terbuka.
Namun, semua itu harus disertai keberanian akademik: membongkar sekat antardisiplin, mengundang dosen teknik berdialog dengan ahli ushul fikih, atau menghadirkan tokoh adat dalam kuliah sosiologi. Effort dan masyaqatnya memang luar biasa.
Kurikulum harus terus diperbarui menjadi living curriculum—hidup, kontekstual, dan berpihak pada kemaslahatan. Secara simultan proses pembelajaran setara dengan proses problem solving–bertemunya mitigasi resiko dengan sejumlah solusi.
Mengukur Dampak
Agar arah integrasi berjalan sesuai cita-cita, dibutuhkan sistem evaluasi yang menyeluruh. Audit kurikulum oleh tim penjaminan mutu bisa menjadi langkah awal untuk memastikan setiap mata kuliah apakah sudah mengurut benang merah antara keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan.
Instrumen penilaian juga perlu dikembangkan: laporan riset agar dinilai tidak hanya dari metodologi dan temuan, tetapi juga dari refleksi etis berbasis maqashid syariah dan dampak sosialnya.
Portofolio mahasiswa dapat mencatat partisipasi dalam pengabdian lintas budaya, sementara survei atas sikap rutinnya dapat menilai perkembangan toleransi, kepedulian lingkungan, dan keterlibatan sosial.
Pada level institusi, keberhasilan kurikulum tiga dimensi dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama yang konkret: meningkatnya publikasi ilmiah dosen yang mengaitkan sains dan etika Islam; munculnya paten teknologi berbasis maslahat; hingga kiprah alumni sebagai penggerak perdamaian lingkungan misalnya.
Sehingga benchmarking dengan kampus global seperti Al-Azhar atau Oxford yang telah mengusung model integrasi lintas-disiplin dapat menjadi rujukan untuk memperkuat visi ini.
Menurut saya kurikulum tiga dimensi–atau kurikulum integrasi, adalah jalan panjang bukan jembatan. Ia merupakan ikhtiar tak henti dalam menjadikan PTKIN sebagai institusi yang mencerahkan—membentuk generasi yang berilmu, beriman, dan berwawasan kebangsaan sekaligus. Materi, metode dan cara penyampaian kurikulum integrasi tentu akan menempuh jalurnya sendiri.
Maka di tangan para perekayasa (curriculum engineering), mahasiswa dan masyarakat terdapat masa depan Indonesia—yang maju teknologinya, luhur akhlaknya, dan kokoh persatuannya. Saya yakin mereka akan menorehkannya untuk Indonesia dengan gagah, penuh makna dan bermartabat.
Khodijah Hulliyah, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Fakultas Sains dan Teknologi (FST) UIN Jakarta.