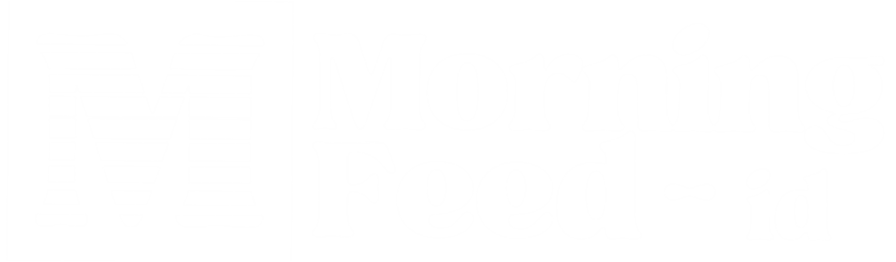Bayangkan sebuah organisme raksasa yang bernapas pelan, mengunyah data, memproses instruksi, lalu mengeluarkan keputusan. Organisme itu bernama birokrasi. Ia tidak pernah tidur, meski sering tampak lamban. Ia menyalurkan sumber daya, mengatur arah gerak Negara, dan pada saat bersamaan menyembunyikan dirinya di balik ribuan meja, dokumen, serta tanda tangan.
Sejak 2020, organisme ini mengalami operasi besar. Pemerintah mengamputasi sebagian “tulang punggung” yang selama puluhan tahun menopang tubuh birokrasi, eselonisasi tingkat III dan IV. Alasannya penyederhanaan. Dengan struktur lebih ramping, birokrasi diharapkan bergerak lincah, efisien, dan responsif. Tetapi seperti operasi besar pada tubuh yang sudah renta, hasil tidak sesederhana harapannya. Lima tahun setelah pembedahan itu, apa yang terjadi? Bagaimana birokrasi kini pasca-eselonisasi?
Kegamangan Pasca Eselonisasi
Eselon bukan sekadar kotak-kotak dalam bagan organisasi. Ia adalah simbol status, identitas sosial, sekaligus jalur karier ASN. Ketika jenjang itu dihapus, banyak aparatur kehilangan orientasi. Mereka tahu apa yang harus dikerjakan, tetapi bingung ke mana arah karier mereka melaju.
Ciri utama penyederhanaan birokrasi yang telah berjalan lima tahun ini adalah pengalihan struktur ke jabatan fungsional. ASN yang kehilangan kotak eselon digeser ke dalam kotak fungsional. Di atas kertas, jabatan fungsional lebih profesional. Setiap posisi diukur dengan angka kredit sesuai kontribusi teknisnya. Namun kenyataan di lapangan kerap berbeda. Banyak jabatan fungsional sekadar menjadi alasan untuk menaikkan tunjangan. Beban kerja tak selalu mencerminkan angka tunjangan yang diterima. Bahkan sebagian jabatan fungsional tidak benar-benar mengerjakan tugas fungsionalnya. Bukan karena tidak mau melakukannya, tapi karena sebagian besar pekerjaan birokrasi sedikit saja yang bersifat fungsional.
Mereka tetap melakukan koordinasi, rapat, tanda tangan, supervisi (pekerjaan khas struktural) tetapi dengan label “fungsional”. Akibatnya, jabatan fungsional terasa seperti kostum dalam sandiwara birokrasi. Kelihatannya fungsional, padahal rasanya tetap struktural.
Alih-alih melahirkan efisiensi, penyederhanaan justru menimbulkan kegamangan. Seperti prajurit tanpa kesatuan, ASN bekerja tanpa kejelasan medan. Dalam rapat-rapat internal, mereka masih menunggu instruksi yang biasanya mengalir secara berjenjang. Kini rantai komando dipotong, tetapi pola pikir lama belum bergeser.
Di sisi lain, Pejabat pimpinan pratama yang terbiasa memimpin sedikit orang dibawahnya dipaksa kembali menjadi komandan lapangan, menangani lebih banyak bawahan, lengkap dengan aneka perilakunya. Namun sebagai pimpinan mereka tidak menyerah, lalu membuat konsep “atasan langsung semu” dengan terminologi ketua tim, pengendali teknis, koordinator, subkoordinator dan semacamnya. Jadilah birokrasi menjadi rantai komando nonformal yang menambah persoalan baru. Birokrasi yang seharusnya menjernihkan peran dan pembagian tugas, justru menjadi keruh tak berpola.
Pemerintah memang bercermin dengan merujuk indeks kepuasan masyarakat atau indeks kinerja ASN. Tetapi angka-angka itu hanya sekedar ilusi daripada kompas sejati. Indeks kepuasan masyarakat menunjukkan tren naik, namun bukan buah dari penyederhanaan struktur. Bisa jadi karena faktor eksternal, misalnya digitalisasi layanan yang digerakkan teknologi swasta, jadi bukan karena birokrasi makin gesit.
Indeks kinerja ASN hanya dilihat dari sekedar tumpukan formulir daring. Pegawai mengisi self-assessment, atasan memberi skor, lalu sistem mengeluarkan angka rata-rata. Angka itu indah di laporan, tetapi sering tidak mencerminkan performa kerja sehari-hari. Seperti menilai kesehatan tubuh hanya dari warna kulitnya, kita lupa memeriksa detak jantung dan tekanan darah.
Untuk memahami kebingungan ini, kita harus melihat bahwa birokrasi Indonesia sebenarnya memiliki dua entitas. Pertama, birokrasi sebagai pembuat regulasi teknis dan operasional. Di sinilah kebijakan ditulis, prosedur disusun, dan detail diatur. Kedua, birokrasi sebagai penyedia layanan publik. Inilah wajah yang langsung berhadapan dengan warga, seperti layanan kesehatan, pendidikan, perizinan, bantuan sosial dan sebagainya.
Penyederhanaan eselonisasi tidak membedakan dua entitas ini. Padahal prinsip yang berlaku pada entitas regulasi tidak sama dengan entitas pelayanan. Regulator membutuhkan jenjang verifikasi agar setiap aturan matang sebelum diterapkan. Sementara penyedia layanan justru butuh kecepatan, fleksibilitas, dan kehangatan interaksi. Dengan satu resep yang sama untuk dua entitas yang berbeda, seperti memberi obat flu untuk patah tulang.
Kita bisa belajar dari Negara lain seperti Jepang misalnya, yang pernah bergulat dengan persoalan serupa. Pemerintah Jepang tidak pernah benar-benar menyingkirkan hierarki. Justru dengan hierarki yang ketat, mereka melatih mekanisme verifikasi berlapis sehingga setiap kebijakan matang sebelum dieksekusi. Namun mereka menyuntikkan disiplin kaizen, perbaikan kecil terus-menerus, agar hierarki tidak berubah menjadi beban.
Begitu pun dengan Korea Selatan. Setelah krisis finansial Asia 1997, mereka mereformasi birokrasi dengan digitalisasi besar-besaran. Alih-alih merombak struktur secara drastis, mereka mengurangi beban hierarki melalui teknologi. Hasilnya, pelayanan publik menjadi cepat tanpa mengorbankan rantai pengambilan keputusan.
Dua contoh ini memberi pesan bahwa penyederhanaan bukan semata soal memangkas jenjang, tetapi bagaimana memastikan setiap simpul birokrasi mampu bekerja efektif dalam berbagai konteks tantangannya.
Perlukah Birokrasi berjenjang? Mengapa sejak awal birokrasi didesain berjenjang?
Banyak yang menganggap hierarki hanya alat memperpanjang rantai komando. Padahal ada logika lain yang lebih dalam yaitu prinsip verifikasi berlapis. Kebijakan publik bukan sekadar keputusan teknis. Ia menuntut perspektif dari level mikro hingga makro. Dari eye view yang melihat detail teknis, hingga helicopter view yang memahami gambaran keseluruhan. Tanpa jenjang, perspektif itu hilang.
Jika sebuah keputusan langsung diambil oleh satu tingkat saja, risiko kesalahan meningkat. Ibarat membangun jembatan hanya dengan sekelompok insinyur tanpa pengawasan sarjana keuangan, struktur mungkin cepat jadi, tetapi rapuh ketika diuji beban. Birokrasi berjenjang adalah mekanisme evolusioner untuk memastikan setiap kebijakan diuji di berbagai lapisan pengetahuan.
Namun kita juga tidak bisa menutup mata terhadap realitas. Rantai komando tradisional memang menjadi problem sepanjang sejarah birokrasi. Setiap instruksi harus melewati banyak meja, sehingga waktu habis untuk paraf dan disposisi.
Akan tetapi teknologi membuat rantai itu semakin kehilangan makna. Atasan dan bawahan bisa berdiskusi lewat pesan instan, rapat daring, atau berbagi dokumen digital kapan saja, tanpa harus menunggu agenda tatap muka. Konsolidasi bisa berlangsung simultan, bukan linear.
Dengan cara ini, kekhawatiran akan misleading semakin minim. Informasi bisa diverifikasi secara kolektif dalam hitungan menit. Maka persoalan kita bukan lagi panjangnya rantai komando, melainkan bagaimana memastikan setiap simpul dalam rantai memiliki kualitas pengambilan keputusan yang mumpuni.
Pertanyaannya kini, apakah birokrasi pasca-eselonisasi akan tumbuh menjadi organisme yang lebih sehat, atau justru terjebak sebagai monster tambal-sulam? Bisa jadi kita sedang berada dalam transisi menuju bentuk baru birokrasi, dari organisme hierarkis menjadi jaringan kolaboratif. Jika dulu birokrasi mirip tubuh dengan kepala, tangan, dan kaki yang bergerak sesuai instruksi pusat, kini ia berpotensi berubah seperti jaringan neuron yang mana setiap simpul memiliki fungsi, tetapi saling terhubung cepat melalui teknologi.
Tetap saja, Tanpa desain yang jelas jaringan bisa kacau, simpul bekerja sendiri-sendiri, dan keputusan justru makin blur. Penyederhanaan eselonisasi adalah eksperimen besar yang belum selesai. Ia membuka peluang, tetapi juga meninggalkan tantangan. Jika pemerintah hanya berhenti pada kosmetik, mengganti label struktural dengan fungsional tanpa menyentuh akar persoalan, birokrasi akan terus bergulat dengan paradoks “ingin ramping tapi tetap gemuk, ingin gesit tapi tetap lamban”.
Mungkin kita perlu melihat birokrasi bukan sebagai mesin yang harus dipangkas atau diperbesar, melainkan sebagai organisme yang harus dipelihara, diajari cara bernapas baru, dan disuntikkan visi segar. Hanya dengan begitu, ia bisa berubah dari sekadar penumpuk kertas menjadi jaringan saraf bangsa yang berpikir cepat, mengambil keputusan matang, dan melayani warga dengan hati.
Martin H. Siagian (ASN Ditjen Bimas Kristen Kemenag RI dan penulis artikel “Perangkap grade tujuh, Refleksi Kritis Satu Dekade Job Grading ASN)