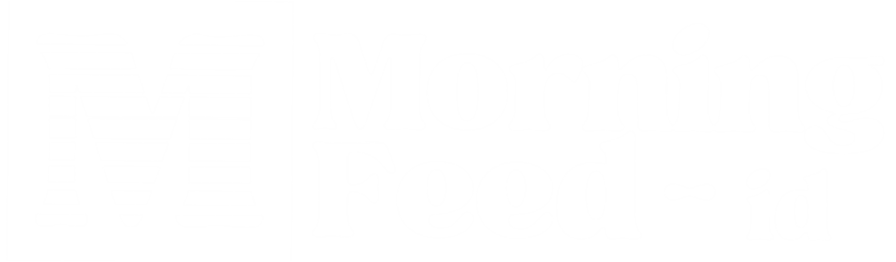Di tengah tantangan lingkungan yang semakin kompleks, mulai dari berkurangnya kualitas air sungai hingga ancaman krisis air bersih masyarakat di Kelurahan Fajar Esuk, Kabupaten Pringsewu, Lampung, memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana budaya dan spiritualitas dapat berpadu dalam menjaga alam. Tradisi Mapak Tuyo, yang dalam bahasa Indonesia berarti “menjemput air”, bukan sekadar ritual tahunan yang penuh warna, melainkan cerminan dari kesadaran ekologis yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari.
Prosesi ini dilaksanakan oleh umat Hindu dengan dukungan aktif dari umat Islam. Mereka beriringan membawa hasil bumi yang disusun rapi menjadi gunungan, mirip seperti tradisi Sekaten di Yogyakarta, menuju tepian Sungai Way Sekampung untuk melakukan penghormatan terhadap air.
Keunikan Mapak Tuyo tidak hanya terletak pada estetika budayanya, tetapi juga pada pesan ekoteologinya. Air yang dijemput bukan sekadar kebutuhan fisik, melainkan simbol kehidupan yang memiliki dimensi spiritual. Dalam ajaran Islam, air adalah tanda kesucian yang digunakan untuk bersuci dan sumber daya yang harus dijaga.
Dalam Hindu, air atau tirtha adalah anugerah suci dari sumber ilahi yang membersihkan lahir dan batin. Prosesi ini menyatukan dua pandangan tersebut dalam satu panggung budaya, menghadirkan rasa syukur kepada Tuhan sekaligus mengingatkan pentingnya merawat ciptaan-Nya. Menghormati air berarti menjaga hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.
Keberlangsungan tradisi ini sangat dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat Fajar Esuk yang multikultural. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, mayoritas penduduk menganut agama Islam (95%), disusul Katolik (3,3%), Protestan (1,3%), Budha (0,3%), dan Hindu (0,2%). Meski umat Hindu merupakan minoritas, partisipasi mereka dalam kehidupan sosial sangat dihargai.
Menurut artikel yang ditulis oleh Eri Purwanti dkk, “Masyarakat di Kelurahan Fajar Esuk selalu saling membantu dalam segala hal, toleransi antar umat beragama yang berbeda sangat tinggi tanpa harus memandang agama, suku, ras, dan adat istiadat yang berbeda.” Kondisi ini mencerminkan apa yang disebut para ahli sebagai multikulturalisme kosmik, di mana setiap kelompok bebas mempertahankan identitasnya, tetapi tetap terhubung dalam pengalaman bersama yang saling menguatkan.
Mapak Tuyo adalah salah satu wujud nyata dari pengalaman bersama itu. Dalam prosesi ini, umat Islam tidak sekadar hadir sebagai penonton, tetapi terlibat aktif memikul gunungan, mengatur jalannya arak-arakan, dan ikut dalam doa bersama. Sebaliknya, umat Hindu juga membuka ruang partisipasi yang luas tanpa memandang perbedaan keyakinan. Harmoni ini tidak tercipta dalam semalam, melainkan hasil dari interaksi yang konsisten dan dukungan tokoh agama serta tokoh masyarakat yang selalu menekankan pentingnya hidup rukun.
Kearifan lokal yang melandasi Mapak Tuyo lahir dari pemahaman mendalam tentang ekologi. Sungai Way Sekampung bukan hanya bentang alam, tetapi nadi kehidupan yang mengairi sawah, menyediakan air minum, dan menopang ekosistem. Karena itu, prosesi Mapak Tuyo selalu diawali dengan membersihkan area sungai, memastikan aliran air tetap lancar, dan mengatur distribusinya untuk pertanian. Tujuan utama kegiatan ini adalah agar masa pengolahan tanam airnya lancar dan cukup. Inilah bentuk nyata prinsip keberlanjutan yang disampaikan dalam bahasa budaya, bukan sekadar jargon lingkungan.
Nilai gotong royong atau sakai sambaiyan juga menjadi inti tradisi ini. Setiap orang mengambil peran sesuai kemampuan ada yang menyiapkan gunungan hasil bumi, ada yang menata jalannya prosesi, dan ada yang memasak makanan untuk para peserta. Anak-anak ikut membantu menghias, remaja mengatur jalannya acara, dan orang tua memberikan arahan. Semua ini membentuk proses pendidikan ekologis dan toleransi yang berjalan alami.
Keterlibatan lintas agama dalam Mapak Tuyo bukanlah hal yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola toleransi yang lebih luas di Fajar Esuk. Dalam tulisan Eri Purwanti dkk, mencatat bahwa umat non-Muslim membantu perayaan Idul Fitri dan Idul Adha, sementara umat Muslim menghormati perayaan Nyepi dengan tidak membuat kegaduhan. Hubungan ini bersifat timbal balik dan dibangun atas rasa saling percaya. Seperti yang diungkapkan Cak Nur dalam Nurkholis (1999), “Toleransi hanya dapat tumbuh pada orang yang memiliki semangat keterbukaan… kesediaan untuk mendengar pendapat orang lain untuk diambil dan diikuti mana yang terbaik.”
Dalam kerangka ekoteologi, Mapak Tuyo menunjukkan bahwa iman kepada Tuhan tidak berhenti pada pengakuan lisan atau ibadah ritual, tetapi menemukan bentuk nyatanya dalam tindakan merawat bumi. Mengotori sungai atau membiarkan sumber air rusak berarti mengkhianati amanah yang telah diberikan Tuhan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebaliknya, membersihkan sungai, menjaga aliran air, dan menggunakan sumber daya secara bijak adalah bentuk ibadah yang tak kalah mulia dari ritual keagamaan.
Tradisi ini juga menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda. Mereka tidak hanya mendengar cerita tentang pentingnya air, tetapi melihat langsung bagaimana masyarakat mempersiapkan dan melaksanakan ritual penghormatan terhadapnya. Dari proses itu, mereka belajar bahwa menjaga alam adalah bagian dari menjaga diri sendiri dan komunitas. Mereka juga menyaksikan bahwa keberagaman bukan penghalang untuk bekerja sama demi tujuan bersama.
Relevansi Mapak Tuyo semakin terasa di tengah krisis lingkungan global. Perubahan iklim telah mengganggu siklus air di banyak wilayah, menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. Polusi sungai mengancam kesehatan dan mengurangi ketersediaan air bersih. Dalam konteks ini, tradisi seperti Mapak Tuyo tidak hanya mempertahankan warisan budaya, tetapi juga menjadi strategi adaptasi yang mengandalkan kekuatan komunitas. Dengan memadukan nilai agama, kearifan lokal, dan aksi nyata, masyarakat mampu membangun sistem perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.
Seorang warga, Ibu Hartati, menggambarkan semangat kebersamaan ini ketika berbicara tentang tradisi lain yang sejiwa dengan Mapak Tuyo, yakni wiwitan panen padi: “Musim panen merupakan salah satu momen yang ditunggu oleh semua warga di Fajar Esuk, tidak hanya petani saja. Warga beramai-ramai ikut serta dalam menyambut musim panen dengan mengadakan wiwitan. Kemudian dari panitia kegiatan membuat tumpengan.” Meski konteksnya berbeda, esensi yang dipegang tetap sama bersyukur, bekerja bersama, dan merayakan kehidupan dengan menjaga sumbernya.
Pengakuan dan penghargaan terhadap keberagaman menjadi fondasi bagi semua. Tulisan ini menegaskan bahwa prinsip-prinsip seperti kesetaraan, keadilan, inklusi, partisipasi, dialog, dan pemahaman telah menjadi bagian dari identitas masyarakat Fajar Esuk. Prinsip-prinsip ini bukan hanya menjaga harmoni sosial, tetapi juga memperkuat komitmen kolektif terhadap kelestarian alam.
Mapak Tuyo mengajarkan bahwa merawat alam bukanlah tugas segelintir orang atau kewajiban yang hanya muncul ketika ada ancaman. Ia adalah laku hidup yang dijalankan bersama, berulang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi ini membuktikan bahwa spiritualitas yang membumi mampu menjembatani perbedaan dan membangun aksi nyata yang melampaui sekat agama maupun budaya. Dari tepian Sungai Way Sekampung, pesan itu terus mengalir: menjaga alam adalah menjaga kehidupan, dan menjaga kehidupan adalah bagian dari iman yang paling tulus.
Agus Mahfudin Setiawan (UIN Raden Intan Lampung)