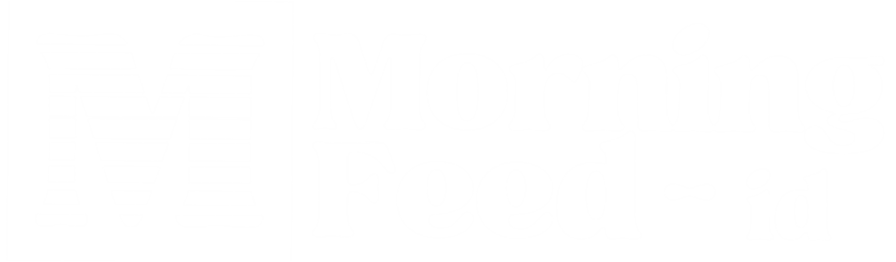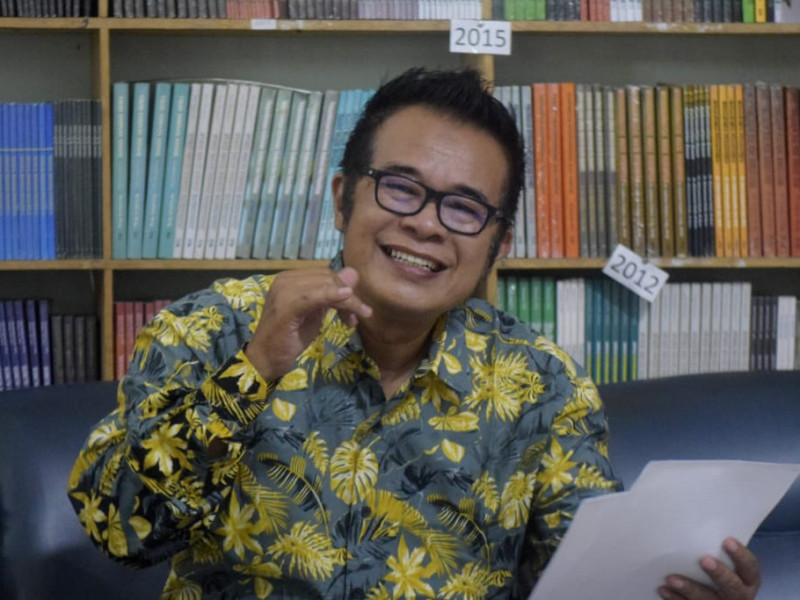Tulisan ini berangkat dari hasil pembacaan dan refleksi terhadap buku baru karya Prof. Dr. Syufaat, M.Ag. dan Enjen Zaenal Mutaqin, M.Ud., Moderasi Beragama dan Ketahanan Keluarga: Model Pemberdayaan Ekonomi Berkelanjutan di Desa Trikarso (Pekanbaru: CV. Pustaka Press, 2025). Buku ini merupakan hasil penelitian dan pendampingan dua dosen UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang menyelami kehidupan warga di Desa Trikarso, Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.
Keluarga: Ruang Awal Moderasi
Pada titik-titik krusial dalam sejarah umat manusia, keluarga selalu menjadi tempat pulang dari guncangan sosial, ekonomi, dan spiritual. Dalam konteks Indonesia, terutama di tengah arus politik identitas dan tekanan ekonomi global, ketahanan keluarga tak hanya penting sebagai unit sosial terkecil, melainkan sebagai medan praksis nilai-nilai moderasi beragama yang membumi.
Namun, perbincangan moderasi sering kali melambung dalam ruang abstraksi: dipresentasikan dalam seminar, dirumuskan dalam dokumen, tetapi jauh dari pengalaman konkret warga. Dalam kondisi semacam itu, moderasi tampak seperti etika negara, bukan bagian dari laku hidup warga. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Karen Armstrong, “Religion has to be brought down to earth” (agama harus diturunkan ke bumi), (Armstrong, 2009: 25).
Keluarga adalah tempat pertama seseorang belajar tentang keteraturan, kasih sayang, konflik, dan cara menyelesaikannya. Di sinilah moderasi beragama sebenarnya dibentuk pertama kali—jauh sebelum seseorang mengunjungi masjid, gereja, vihara, atau pura. Seseorang tidak menjadi moderat karena doktrin semata, melainkan karena mengalami bagaimana perbedaan dihargai dan dihayati di ruang rumah.
Ketahanan keluarga bukan hanya tentang daya tahan ekonomi, tetapi lebih dalam lagi: kemampuan spiritual dan sosial untuk menciptakan kehangatan, saling menghargai, dan dukungan lintas peran. Hal ini sejalan dengan konsep al-usrah dalam Islam, yang bukan sekadar institusi pernikahan, tetapi sebagai madrasah nilai—sebuah sekolah pertama untuk laku tauhid, akhlak, dan tasamuh.
Namun dalam praktiknya, ketahanan ini tidak bisa berdiri sendiri. Ia bergantung pada ekosistem yang lebih luas: komunitas, ekonomi lokal, hingga sistem pendidikan dan agama. Dalam kaitan inilah kita bisa belajar dari kasus Trikarso.
Trikarso: Islam Kultural dalam Ekonomi Komunitas
Trikarso adalah desa di Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Letaknya terpencil, tidak tersorot media, namun menyimpan kekayaan spiritual dan sosial yang penting. Dari desa ini, model ketahanan keluarga dan praksis moderasi tumbuh secara organik melalui komunitas petani jamur. Mereka tidak hanya bekerja untuk bertahan hidup, tetapi juga membangun solidaritas sosial dan keberdayaan ekonomi dengan landasan nilai-nilai Islam yang hidup dalam keseharian.
Warga Trikarso tidak banyak berbicara tentang “moderasi” dalam istilah akademik, namun nilai-nilai seperti kerja sama lintas perbedaan, kesederhanaan hidup, dan etos kerja yang jujur menjadi bagian dari kehidupan mereka. Hal ini merefleksikan Islam kultural sebagaimana dijelaskan oleh Greg Fealy dan Sally White, yakni bentuk ekspresi Islam yang membumi dalam tradisi lokal dan bersifat akomodatif (Fealy & White, 2008: 6).
Pusat kegiatan masyarakat Trikarso tidak hanya di masjid, tetapi juga di kebun jamur, dapur, dan balai desa. Di sanalah mereka berdiskusi, belajar, dan berbagi. Islam yang dijalani adalah Islam yang menghidupi, bukan sekadar yang diyakini. Praksis inilah yang disebut taqwa sosial: mengintegrasikan iman dengan tindakan nyata.
Model ini menarik karena berangkat dari kekuatan internal warga dan keteladanan harian. Misalnya, ketua kelompok tani jamur memberi pelatihan gratis bagi warga baru dan membagikan bibit tanpa pamrih. Di lain sisi, keluarga-keluarga di Trikarso juga mempraktikkan gotong royong dan prinsip syura dalam pengambilan keputusan rumah tangga dan komunitas.
Moderasi Beragama sebagai Hasil, Bukan Instruksi
Salah satu kelemahan pendekatan negara dalam membumikan moderasi beragama adalah menjadikannya sebagai proyek top-down. Masyarakat dijadikan objek dari program, bukan subjek yang berdaya. Di Trikarso, kita justru menyaksikan moderasi tumbuh dari bawah: dari relasi keluarga yang sehat, komunitas yang suportif, dan ekonomi lokal yang adil.
Nilai-nilai Islam seperti ikhlas, tawakal, syura, dan rahmah terwujud dalam kegiatan konkret: berbagi bibit jamur, gotong royong membangun kumbung, hingga menjaga harga agar tetap adil. Tanpa label “program keagamaan”, warga menunjukkan keteladanan dan keberlanjutan nilai.
Amartya Sen menyebut pendekatan semacam ini sebagai capability approach (pendekatan kemampuan), yakni menilai kemajuan dari sejauh mana orang memiliki kebebasan nyata untuk hidup sesuai nilai yang mereka anggap penting (Sen, 1999: 18).
Di titik ini, peran negara seharusnya bukan menjadi pengatur utama, tetapi fasilitator proses. Pendekatan partisipatif dan pendampingan berbasis komunitas lebih efektif dalam menghidupkan nilai moderasi karena lahir dari realitas, bukan dari konsep.
Islam Bekerja, Bukan Sekadar Berkata
Di Trikarso, agama bukanlah sistem simbol, tapi jalan hidup yang bekerja. Kerja adalah ibadah, dan ibadah adalah kerja. Doa tak hanya diucapkan di sajadah, tetapi dijalankan di ladang. Solidaritas, kejujuran, dan pembagian hasil yang adil menjadi ijtihad sosial harian.
Model keberagamaan ini sejalan dengan Islam berkemajuan versi Muhammadiyah, dan juga sejiwa dengan nilai rahmatan lil ‘alamin. Namun warga Trikarso tidak menyebutnya demikian. Mereka melakukannya sebagai kelaziman yang dilandasi iman.
Dengan itu, Trikarso membuktikan bahwa moderasi bisa lahir dari ladang, dapur, dan obrolan panen. Paulo Freire menyebut, “Social transformation is only possible when theory and practice come together in critical consciousness” (Transformasi sosial hanya mungkin terjadi ketika teori dan praktik bersatu dalam kesadaran kritis), (Freire, 2005: 66).
Menata Ulang Arah Kebijakan Moderasi
Pengalaman Trikarso mengajarkan bahwa ketahanan keluarga adalah fondasi utama bagi moderasi beragama. Namun ketahanan ini tidak cukup dibangun di ranah domestik, melainkan harus didukung oleh komunitas yang hidup, ekonomi lokal yang adil, dan spiritualitas yang membumi.
Jika Kementerian Agama ingin membumikan moderasi, maka pendekatannya perlu ditransformasikan dari narasi ke aksi, dari ruang rapat ke ruang keluarga. Kita harus belajar dari pengalaman warga, memperkuat basis ekonomi komunitas, dan merangkul Islam kultural sebagai kekuatan nyata.
Sebab moderasi bukan slogan, melainkan jalan hidup. Dan seperti di Trikarso, jalan itu dimulai dari keluarga yang sederhana, dapur yang hangat, ladang yang subur, dan iman yang bekerja.***
Abdul Wachid B.S.( Penulis adalah penyair, Guru Besar Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan Ketua Lembaga Kajian Nusantara Raya (LK Nura) di Purwokerto.)