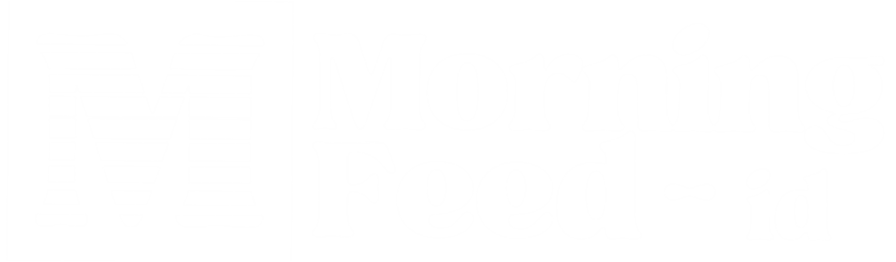Anselmus Dore Woho Atasoge (Staf Pengajar Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende)
Asta Protas oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar bukanlah sekadar rencana kerja lima tahunan Kementerian Agama RI. Delapan program prioritas ini membawa semangat perubahan yang berdampak langsung pada kehidupan publik umat beragama. Di dalamnya termuat agenda-agenda besar: dari penguatan kerukunan dan ekoteologi, pemberdayaan pesantren dan ekonomi umat, hingga digitalisasi tata kelola. Setiap protas bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi manifestasi spiritual yang menghubungkan nilai-nilai keagamaan dengan keadaban sosial.
Salah satu wajah paling konkret dari Asta Protas adalah pengarusutamaan literasi sebagai wahana pembebasan spiritual dan sosial. Literasi dalam konteks ini bukan sekadar kemampuan baca tulis, melainkan sebuah praksis reflektif yang membangun kesadaran keimanan dan transformasi budaya. Gagasan tentang perpustakaan sebagai “rumah kedua”, seperti yang diusung oleh Kepala Kemenag Flores Timur Yosef Aloysius Babaputra, menjadi titik kunci dalam menjelmakan protas ini sebagai gerakan kemanusiaan. Ketika buku-buku ditempatkan di ruang pelayanan publik, ia bukan hanya memperluas wawasan, tetapi juga memperkuat jalinan solidaritas antarprofesi dan antargenerasi.
Dalam pandangan sosiologi pendidikan, perpustakaan adalah ruang sosialisasi pengetahuan dan pembentukan habitus keilmuan. Di Flores Timur, gagasan Babaputra menggugah perpustakaan dari tidur panjangnya: ia tidak lagi pasif sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi aktif sebagai arena tumbuhnya nilai kolektif. Kolaborasi Kemenag dengan Dinas Perpustakaan dan PGRI di Flores Timur menjadi tonggak lahirnya komunitas pembelajar yang berakar pada refleksi spiritual dan praktik budaya literasi. Literasi di sini berpadu dengan spiritualitas, menghasilkan pemahaman iman yang menghidupkan dan bersifat partisipatif.
Pierre Bourdieu (1990) menyebut perpustakaan sebagai arena produksi dan distribusi modal kultural. Ketika koleksi pustaka diakses oleh ASN, guru, dan masyarakat, legitimasi intelektual terdistribusi dan memperkuat kapasitas pelayanan publik. Namun, Bourdieu juga mengingatkan bahwa distribusi pengetahuan seringkali tidak merata. Maka, perpustakaan harus menjadi ruang demokratis yang menembus sekat-sekat eksklusivitas. Penempatan 200 judul buku secara terbuka di Flores Timur yang digagasa Kantor Kementerian Agama Flores Timur dalam kerja sama dengan Dinas Perpustakaan Daerah dan PGRI Flores Timur menjadi aksi nyata bahwa literasi bukan milik elite, tetapi hak bersama untuk bertumbuh.
Emile Durkheim (1922) menempatkan pendidikan sebagai wahana penginternalisasian nilai kolektif. Perpustakaan, dalam kerangka Durkheim, menjadi institusi moral yang memperkuat kohesi sosial melalui interaksi dengan teks. Di Flores Timur, ruang baca menjadi titik temu antarprofesi: ASN, guru, penyuluh agama, dan warga berbagi waktu dan wawasan untuk memahami dunia secara lebih dalam dan mawas. Literasi menjadi ritual sosial yang mengukuhkan solidaritas, bukan hanya transfer pengetahuan.
Gagasan Selo Soemardjan (1964) tentang perubahan sosial melalui pergeseran nilai dan perilaku juga terasa hidup dalam ekosistem literasi Flores Timur. Ketika guru dan penyuluh mulai menulis refleksi pelayanan mereka, budaya lisan berubah menjadi budaya menulis. Perpustakaan tidak lagi hanya menjadi gudang buku, tetapi menjadi pabrik pengetahuan yang mengangkat nilai-nilai lokal dan spiritualitas publik. Kemenag melalui Asta Protas mendorong perubahan ini dengan memperkuat literasi tematik dan pelatihan pustakawan agar ruang baca benar-benar hidup dan relevan.
Dian Sinaga, dosen Universitas Padjadjaran, menyebut perpustakaan sebagai agen transformasi yang mengubah masyarakat dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi terampil. Namun ia menegaskan, koleksi pustaka harus kontekstual. Di Flores Timur, Kemenag punya peluang besar memperkuat pustaka berbasis kearifan lokal, ekoteologi, dan moderasi beragama. Ketika literasi bertaut dengan konteks dan spiritualitas, ia menjelma menjadi kekuatan sosial yang mengubah cara pandang masyarakat terhadap dunia dan terhadap sesama.
Dalam alur besar pembangunan nasional, perpustakaan adalah ruang hening yang merawat akal dan menumbuhkan harapan. Ketika perpustakaan ditempatkan di jantung pelayanan publik dan dimaknai sebagai rumah kedua, ia menjadi simpul peradaban yang menghubungkan iman dan ilmu, tradisi dan inovasi. Asta Protas dan gerakan literasi Flores Timur menunjukkan bahwa keheningan tidak harus pasif. Ia bahkan bisa menjadi ruang reflektif yang mencipta, menyatukan, dan membebaskan.
Gerakan ini memberi pelajaran bahwa spiritualitas bukanlah aktivitas batin semata, melainkan energi sosial yang hidup dalam teks, ruang, dan tindakan. Ketika Asta Protas menjangkau perpustakaan, rumah ibadah, pesantren, dan ruang komunitas, maka Kemenag RI sedang menata ulang arsitektur spiritual publik: dari birokrasi menuju belarasa, dari kebijakan menuju kebijaksanaan. Di titik ini, literasi tidak sekadar agenda pendidikan, tetapi janji perubahan yang berakar pada nalar, menyentuh nurani, dan melahirkan harapan bersama.***
Anselmus Dore Woho Atasoge (Staf Pengajar Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende)